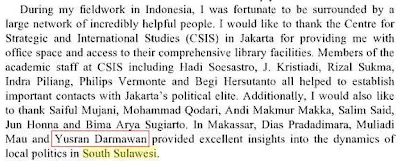LEMBARAN kertas itu terlihat buram dan dimakan usia. Warnanya kekuningan dan sudah lapuk di sana-sini. Sampulnya warna biru, namun seolah sudah berwarna kehitaman. Saat melihat lembaran itu dari dekat, saya menyaksikan aksara Arab tercatat di situ. Perlahan, saya mencoba membuka lembar naskah itu secara hati-hati. Saya membayangkan Robert Langdon sedang berdebar-debar saat membuka naskah kuno karya Galileo Galilei di Vatikan. Tapi ini lain. Ini adalah naskah kuno di Pulau Buton.
LEMBARAN kertas itu terlihat buram dan dimakan usia. Warnanya kekuningan dan sudah lapuk di sana-sini. Sampulnya warna biru, namun seolah sudah berwarna kehitaman. Saat melihat lembaran itu dari dekat, saya menyaksikan aksara Arab tercatat di situ. Perlahan, saya mencoba membuka lembar naskah itu secara hati-hati. Saya membayangkan Robert Langdon sedang berdebar-debar saat membuka naskah kuno karya Galileo Galilei di Vatikan. Tapi ini lain. Ini adalah naskah kuno di Pulau Buton.Demikian pengalaman saya saat tadi berkunjung ke rumah Abdul Mulku Zahari (almarhum), mantan Sekretaris Sultan Buton yang terakhir. Anak Mulku, yang bernama Al Mujazi Mulku, masih menyimpan semua naskah kuno yang diwariskan ayahnya sejak mangkat sejak puluhan tahun silam. Isi naskah itu macam-macam. Mulai dari surat-surat Kesultanan Buton dengan Belanda, surat-surat dari sultan pada pejabat kesultanan di daerah, naskah ajaran agama, hingga naskah tentang pengobatan. Semuanya tersimpan rapi, namun kondisinya sudah mulai memprihatinkan.
Mungkin, sebagian dari kita menganggap naskah sebagai hal yang sepele. Coba bayangkan, apa jadinya jika naskah itu lenyap dari bumi? Mungkin kita akan menyaksikan apa yang disebut Ericd Wolf sebagai “masyarakat tanpa sejarah.” Masyarakat yang tak punya visi serta jalan terang dan senantiasa dicucuk hidungnya oleh bangsa-bangsa lain. Akan menjadi masyarakat yang tak pernah mengambil hikmah dari masa ribuan tahun sebelumnya dan terjerembab pada kebodohan yang selalu terulang dalam sejarah. Akan menjadi masyarakat –yang sebagaimana dikatakan Goethe--, yang hidup tidak menggunakan akalnya. Masyarakat yang bebal!
Makanya, saya memposisikan naskah sebagai khasanah Kesultanan Buton yang hingga kini masih lestari. Naskah-naskah itu menjadi mata air sejarah, menjadi satu-satunya jembatan yang menghubungkan kita dengan masa silam. Melalui naskah, kita bisa belajar banyak, mencatat ulang kejadian yang lampau, sekaligus menambah tebal kebanggaan dan harga diri bangsa. Melalui naskah tersebut, masa silam bisa dijernihkan dari berbagai klaim sepihak, yang terkadang menambah-nambah atau mengurang-ngurangi peran satu kelompok masyarakat dalam sejarah.
Untuk itu, selayaknya penghargaan disematkan kepada Al Mujazi Mulku yang setia memelihara naskah tersebut. Ia menyelamatkan naskah itu semata-mata demi menjaga amanah orangtuanya agar tetap menjaga kumpulan kertas-kertas tua yang mulai lapuk tersebut. Mujazi tahu bahwa penyelamatan naskah itu tidak mempertebal kocek pribadinya. Tetapi ia tetap ikhlas menjagai semua naskah itu sebab didasari keyakinan bahwa kelak generasi baru Buton akan mengenali masa silamnya melalui naskah yang dijagainya tersebut. Naskah itu akan menjadi benda yang berharga dan memantik keingintahuan banyak orang.
 Mujazi banyak bercerita kalau dirinya selalu dikunjungi para peneliti asing. Saat mengunjunginya tadi, ia baru saja menerima kunjungan seorang peneliti asal Australia yang riset tentang Buton. Dengan gayanya yang ramah, Mujazi menemani peneliti itu dan memberikan informasi yang dibutuhkannya, meskipun untuk itu ia tidak dibayar. Keramahan itu terkadang dibalas dengan tidak sepadan oleh para peneliti. Mujazi dengan fasihnya menyebut banyak peneliti yang membisniskan koleksi naskahnya, tanpa memberikan sedikitpun penghargaan padanya sebagai penjaga naskah.
Mujazi banyak bercerita kalau dirinya selalu dikunjungi para peneliti asing. Saat mengunjunginya tadi, ia baru saja menerima kunjungan seorang peneliti asal Australia yang riset tentang Buton. Dengan gayanya yang ramah, Mujazi menemani peneliti itu dan memberikan informasi yang dibutuhkannya, meskipun untuk itu ia tidak dibayar. Keramahan itu terkadang dibalas dengan tidak sepadan oleh para peneliti. Mujazi dengan fasihnya menyebut banyak peneliti yang membisniskan koleksi naskahnya, tanpa memberikan sedikitpun penghargaan padanya sebagai penjaga naskah.Ia lalu menunjukkan buku Katalog Naskah Buton yang disusun para pengajar Universitas Indonesia (UI) dan diedit oleh Prof Achdiati Ikram. “Buku ini dikomersialkan. Dijual di mana-mana. Namun, saya sebagai pemilik naskah tidak pernah diberitahu, apalagi diberi royalti,” katanya. Kakak Mujazi juga mengiayakan. Ia sendiri membeli buku itu di Medan. Sementara keluarganya sama sekali tidak mendapatkan royalty atas penerbitan buku. Mujazi juga menyebut nama beberapa profesor asal Malaysia yang nyaris ‘mencuri’ naskah tersebut. “Saya tidak beri izin ketika mereka hendak memotret naskah itu. Saya punya pengalaman ditipu oleh peneliti malaysia,” katanya.
Keikhlasan Mujazi dalam menjaga naskah kuno Buton adalah sesuatu yang patut diacungi jempol. Puluhan tahun menjaga naskah dan museum daerah Buton, ia tidak menerima bayaran memadai. Saya tak mau banyak memberi janji, sebagaimana para peneliti lainnya. Saya hanya bergumam dalam hati, jika kelak saya bertemu pejabat, saya akan minta supaya Mujazi mendapatkan gaji bulanan sebagai penjaga naskah kuno yang menjaga warisan bagi generasi Buton hari ini.(*)