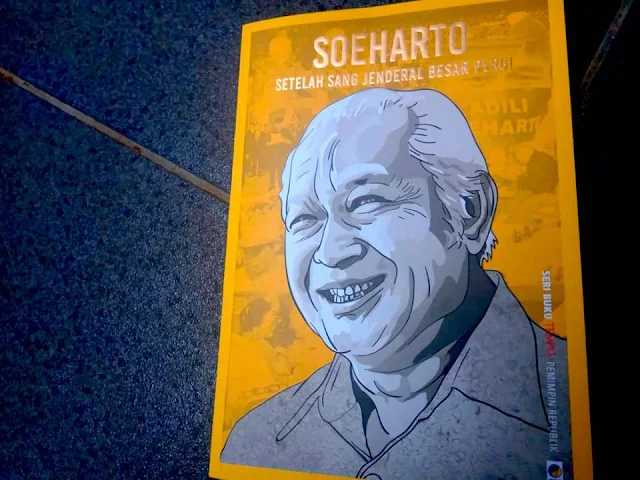JIKA saja kawan itu tidak mengaku terus terang, mungkin saya tidak akan tahu kalau namanya tercatat sebagai salah seorang calon anggota legislatif. Setiap hari, saya menyaksikan postingannya yang menjelekkan pemerintah. Apa pun informasi negatif yang diterimanya, langsung dibagikan ke mana-mana, tanpa dinalar.
Kepadanya saya sampaikan bahwa publik media sosial di Indonesia terbagi atas dua kelompok besar. Satu mendukung pemerintah, satunya adalah oposisi. Jika dirinya selalu melempar postingan negatif pada satu pihak, maka sudah pasti dirinya tidak akan didukung oleh kelompok itu.
Malah, antipati akan muncul pada dirinya. Dia bisa disebut penghasut, penebar hoaks, atau barangkali dianggap biang perpecahan. Jika bernasib sial, dia bisa saja diperkarakan dan kemudian masuk penjara. Saat itu, jangankan terpilih, bisa menjadi manusia bebas saja akan jadi impian.
Di sisi lain, kubu yang sealiran pemikiran dengannya juga belum tentu akan memilihnya. Sebab ada banyak orang sepertinya yang memilih jadi martir di media sosial. Dalam kerumunan itu, dia tidak akan diingat. Begitu capres terpilih, dia akan mudah dilupakan sebagaimana kekeringan yang dihapuskan hujan sehari.
Kepadanya saya menyarankan untuk fokus pada medan tempur yang sedang dimasukinya. Daripada sibuk dalam perang besar antara dua kelompok di pusat, dengan amunisi kuat yang dipasok para pemodal, lebih baik dia fokus pada arena kecil perang yang akan dimasukinya.
Lebih baik dia fokus pada pemilihnya, memetakan segmen mana yang hendak dimasuki, kemudian mulai merencanakan strategi. .
Sejauh yang saya amati, hanya ada tiga cara bagi seorang politisi mendekati konstituennya.
Pertama, langsung mendekati konstituen. Biasanya dilakukan melalui blusukan, temu kader, pengobatan gratis, atau mendatangi rumah ke rumah. Strategi ini butuh biaya dan juga waktu. Apalagi kalau daerah pemilihannya punya banyak gunung dan lembah. Bisa-bisa Anda gak jadi politisi, tapi jadi pendaki gunung.
Kedua, melalui tokoh berpengaruh. Sebab masyarakat kita masih patron-client sehingga sejumlah orang dianggap punya pengaruh ke orang lain. Tapi, cara ini juga berisiko transaksional. Sering kali tokoh berpengaruh tidak memberi dukungan secara gratis. Lain halnya kalau keluarga Anda pernah memberi utang pada tokoh itu. Dijamin gratis.
Ketiga, melalui media. Saya mencatat ada beberapa perubahan muncul dalam Pemilu ini. Di antaranya adalah kian meredupnya pengaruh media mainstream seperti koran. Dahulu, Anda cukup menjalin relasi dengan bos perusahaan media, atau redaktur, maka dijamin Anda akan terkenal. Sekarang strategi itu tidak bisa lagi jadi satu-satunya sandaran.
Bahkan, sering beriklan di media online juga tidak bisa jadi strategi utama. Mengapa? Sebab media online tidak merinci dengan jelas iklan Anda dilihat berapa orang, dari daerah mana saja, apakah itu masuk dapil anda atau bukan.
Media online juga tidak memberi informasi sejauh mana out-take atau impresi orang-orang yang melihat iklan, juga tidak akan memberi informasi bagaimana outcome atau respon dan masukan orang-orang yang menyaksikannya.
Menurut saya, cara paling efektif dan murah untuk menyapa konstituen adalah melalui media sosial. Tak perlu mengeluarkan biaya sebesar membuat balio dan memajangnya di jalan-jalan. Cukup sedikit biaya untuk membeli kuota internet, juga fasilitas Google Adsense atau Facebook Ads.
Setiap saat Anda bisa menyapa orang-orang dan meyakinkan mereka untuk memilih Anda. Di situ, generasi milenial selalu berkumpul dan saling berbagi informasi, mulai dari makanan hingga pilihan politik. Jika dikelola dengan benar, postingan media sosial akan seperti air menetes yang secara perlahan akan membelah batu.
Beberapa pakar sudah menyatakan, pemenang Pemilu mendatang adalah mereka yang paling banyak didukung generasi milenial. Jika ingin memenangkan generasi milenial, maka masuklah pada ekosistem digital di mana generasi ini berkumpul. Karakteristik generasi ini adalah senantiasa aktif dan berinteraksi di media sosial. Kuncinya adalah kuasai media sosial.
Apakah waktu yang ada cukup? Iya. Waktu tujuh bulan hingga pemilu yakni April mendatang bisa efektif digunakan untuk memperbanyak postingan dan merancang konten bagus yang bisa viral dan membuat Anda disukai.
Di era media sosial, konten bagus ibarat currency atau mata uang yang akan membuat Anda terkenal. Content is the king. Konten adalah raja yang akan menentukan sejauh mana popularitas Anda di media sosial.
Tantangannya adalah bagaimana membuat konten yang bagus dan disukai, sehingga viral dan disebarkan ke mana-mana. Setelah punya konten yang disukai, langkah selanjutnya adalah perbanyak interaksi, kemudian bangun digital tribe atau kelompok relawan yang akan menjadi perpanjangan tangan Anda di media sosial.
Makin banyak interaksi, maka Anda makin disukai. Anda punya peluang besar untuk dipilih.
***
DI satu warung kopi yang semilir angin terasa sejuk, saya bertemu kawan politisi itu. Dia seorang yang aktif di media sosial. Dia berterus terang kalau postingannya tidak pernah disukai lebih dari 100 orang. Kadang-kadang dia meminta teman-teman dekatnya untuk menyukai postingannya. Dirinya tidak mengetahui karakteristik media sosial, serta bagaimana menyusun konten yang tepat.
Menguasai media sosial tidaklah semudah apa yang dikhotbahkan para akademisi di kampus-kampus. Beruntung, saya banyak bersahabat dengan para influencer yang setiap posting sesuatu akan disukai ribuan orang.
Saya pun bisa dikategorikan sebagai influencer yang sekali posting akan dibagikan banyak orang. Teman itu tahu kalau beberapa konten yang saya buat sering viral dan disebar banyak orang.
Kepada teman itu saya jelaskan bahwa banyak orang mengira, dengan memperbanyak postingan, maka dia sudah eksis. Orang-orang ini lupa kalau media sosial adalah ruang yang paling demokratis. Semua netizen punya hak yang sama untuk menyukai dan tidak menyukai semua postingan.
Ketika suka, maka mereka akan meninggalkan jejak berupa “like.” Ketika tidak suka, mereka akan cuek saja sehingga postingan itu merana dan tidak dilihat satu pun. Media sosial, seperti Facebook, punya algoritma sendiri yang akan menampilkan semua postingan di halaman depan orang yang menyukainya.
Semakin sering Anda mengklik postingan seseorang, maka apa pun yang diposting orang itu akan selalu tampil di halaman depan media sosial Anda. Jika Anda sering menyukai postingan saya, yakinlah, apa pun yang saya bagikan pasti akan muncul di beranda. Iya kan?
Nah, hal yang sama berlaku pada orang lain. Ketika tidak pernah menyukai postingan Anda, maka pastilah postingan Anda tidak akan tampil di halaman depan. Meskipun Anda berkawan dengannya. Sistem algoritma Facebook yang mengatur itu.
Sejauh pengamatan saya, para politisi mengira apa yang mereka tampilkan akan selalu disukai orang lain. Saya suka senyum-senyum sendiri saat menyaksikan foto politisi yang sudah di-make over menjadi jauh lebih ganteng sehingga mirip aktor Korea. Dia pikir orang akan simpati dengan foto yang sudah diedit sotosop.
Lebih sering saya lihat postingan politisi yang menampilkan dirinya sebagai sosok religius. Hampir semua politisi memajang foto dengan memakai kopiah dan baju koko. Politisi perempuan selalu memakai hijab. Malah, di satu tempat di Sulawesi, beberapa politisi berpose dengan tasbih di tangan. Personal branding yang hendak dibangun adalah sebagai sosok religius dan bisa dipercaya.
Bagi masyarakat yang mengenal figur-figur itu, maka foto mereka di media sosial sering jadi bahan olok-olok. Seorang preman kok jadi mendadak religius. Seorang yang sombong kok mendadak tersenyum dan ramah. Postingan hal-hal baik seperti ini belum tentu akan disukai, sebab semua orang melakukan hal yang sama.
***
APA yang harus dilakukan untuk bisa menghasilkan konten viral? Dalam buku Gara-Gara Facebook, Dewa Eka Prayoga, yang sukses meraup miliaran dari belanja online melalui media sosial, mengatakan, cara praktis membuat konten viral adalah: “Ciptakan sesuatu yang membuat orang lain ingin membagikannya secara suka rela.”
Nah, sesuatu yang viral itu tidak mungkin berbentuk editan foto wajah ganteng atau cantik disertai kalimat tentang diri yang hebat. Sesuatu yang viral itu juga tidak mungkin berupa gambar diri di luar negeri atau pose dengan tokoh-tokoh hebat. Juga tidak mungkin pamer kekayaan atau kehebatan, juga pamer religiusitas.
Bukan pula melalui postingan yang isinya kebencian pada satu orang. Sesuatu yang viral itu adalah hal-hal yang sederhana, dekat dengan orang-orang, serta menyimpan pelajaran dan inspirasi.
Orang akan gampang membagikan sesuatu ketika dirasakannya sesuatu itu bermanfaat, berguna bagi dirinya, serta menginspirasi orang lain. Postingan itu haruslah sesuatu yang bisa membuat orang lain melihat lebih jernih, belajar dari hal biasa, dan menyentuh hatinya.
Ketika Anda sukses membuat konten seperti itu, maka tak perlu meminta orang lain membagikannya. Sebab orang akan suka rela membagikannya ke mana-mana.
Trend kampanye bagi dunia politik dan bisnis adalah soft campaign, yakni kampanye yang soft sehingga tidak terasa seperti kampanye. Selama ini kita mengenal hard campaign yakni serupa penjual obat yang memperkenalkan produknya dengan heboh sebagai produk terbaik. Di era soft campaign, orang tidak lagi spesifik menawarkan sesuatu, namun memberikan kebaikan, layanan, nilai, dan membangun relasi yang bermanfaat.
Dalam kaitan soft campaign, Anda tak perlu menjelaskan kehebatan Anda, tapi bagikanlah hal-hal sederhana yang bisa membuat orang tergugah. Caranya adalah hadirkan sesuatu yang mengejutkan, buat orang-orang bangga dengan dirinya bahkan sesederhana apa pun, buat mereka tertawa gembira dan bahagia ataupun sedih melalui apa yang Anda bagikan.
Kuncinya terletak pada story-telling yakni bagaimana bercerita dengan menarik sehingga disukai orang lain.
Tak perlu rumit-rumit, mulailah dari cerita tentang Anda sendiri. Dalam perjalanan kehidupan setiap orang, selalu saja ada episode menarik, pengalaman, atau perjumpaan dengan sesuatu yang penuh menarik.
Bagikanlah kepada banyak orang pengalaman dan amatan itu. Berceritalah apa adanya, jangan terlalu mendewakan diri sebagai pahlawan, jadilah orang biasa yang berbagi hal biasa. Sesekali jadikan diri sebagai bahan olok-olok. Dengan cara ini, akan terbangun kedekatan sehingga orang-orang akan menyukai Anda.
Dalam konteks politik dan pemasaran, inilah yang disebut personal branding, yakni sejauh mana Anda mendefinisikan diri, dan bagaimana Anda ingin orang lain melihat Anda.
***
JIKA Anda seorang politisi yang ingin membangun penggemar dan relawan di media sosial, saya merekomendasikan beberapa hal yang bisa diterapkan.
Pertama, buat narasi tentang siapa Anda. Tentukan citra diri apa yang hendak Anda tampilkan, kemudian turunkanlah narasi itu dalam bentuk postingan, meme, video, infografis, serta perspektif di berbagai kanal media sosial. Sederhanakan narasi itu sehingga bisa dipahami semua kalangan.
Kedua, buat pemetaan tentang para netizen. Pahami lokasi yang menjadi daerah pemilihan Anda, kenali budaya dan tradisi, juga kebiasaan-kebiasaan di lokasi itu. Usahakan punya informasi mendalam tentang masyarakat di lokasi itu sehingga Anda bisa merencanakan postingan yang bisa menyentuh sasaran. Setiap kali Anda posting, bangun interaksi dan dialog sehingga terbentuk pasar bagi setiap ide-ide Anda.
Ketiga, buat manajemen postingan yang baik. Tentukan kapan setiap postingan dikeluarkan. Perbanyak kisah-kisah, narasi, dan cerita sederhana sebab postingan itu punya potensi disukai banyak orang.
Keempat, gunakan fasilitas Facebook Ads sebab memungkinkan kita untuk menentukan target postingan itu bisa dilihat warga di satu daerah pemilihan, serta bisa menginformasikan dengan detail bagaimana impresi dan kesan orang-orang.
Kelima, selalu lakukan evaluasi pada semua postingan. Amati dengan detail, mana yang disukai dan tidak disukai. Terbuka pada kritik dan masukan demi penyempurnaannya. Siapkan banyak jurus dan strategi untuk silaturahmi digital. Posisikan diri Anda sebagai seorang warga biasa yang ingin bangun relasi dengan siapa saja, apapun pilihan politiknya.
Jika langkah-langkah ini sudah dilakukan, namun belum maksimal, itu pertanda sudah waktunya Anda mengontak saya atau siapa saja untuk berdiskusi. Sebab seperti kata Thomas L Friedman dalam buku Thank Your for Being Late, di era Artificial Intelligent (AI), kita membutuhkan satu tim yang punya kapasitas Intelligent Assistant (IA).
Maksudnya, era AI membutuhkan kapasitas IA. Kegiatan media sosial sebaiknya diperkuat dengan satu tim kreatif yang selalu bisa memberi penguatan dan strategi. Tim ini bisa merancang strategi dan menjadi wakil Anda dalam mendekati konstituen.
Tim ini juga melakukan evaluasi, melakukan riset konten yang disukai khalayak, juga rajin merawat hubungan dengan para netizen yang akan jadi konstituen Anda.
Dengan menguasai media sosial, maka selangkah kaki Anda ke arah kemenangan. Sebab politik tidak selalu terkait gelontoran duit. Politik tidak terkait keturunan. Politik adalah arena untuk memenangkan kesan. Politik adalah bagaimana menanamkan kesadaran dalam diri orang-orang bahwa Anda adalah orang tepat untuk posisi tertentu.
Media sosial adalah koentji.