 |
| Afrial Tabrani saat memberikan presentasi |
LELAKI itu akhirnya datang juga. Ratusan
orang yang hadir di salah satu ruangan di Hotel Menara Peninsula, Slipi,
Jakarta, sontak berdiri lalu memberikan aplaus. Kehadirannya dinanti-nanti. Ia
serupa oase yang mengatasi rasa haus banyak orang yang sejak awal datang telah
menanti kedatangannya. Seorang MC menyebut namanya dengan suara keras
menggelegar. Ia diperkenalkan sebagai Afrial Tabrani.
Sepintas, Afrial tak beda dengan orang
lain yang hadir di forum itu. Ia memasuki ruangan dengan mengenakan pakaian blazer
hitam dengan garis keemasan, serupa jas yang pernah dikenakan Michael Jackson. Kulitnya
nampak agak gelap. Perawakannya tidak seberapa tinggi. Rambutnya dipotong
tipis. Ia datang dengan wajah yang cerah. Senyum tak lepas dari bibirnya. Namun
di forum yang bertemakan Bussiness Opportunity Meeting (BOM) itu, ia adalah
magnit pertemuan. Kehadirannya ditunggu banyak orang.
Mereka yang datang ingin menyaksikannya
secara langsung. Mereka juga ingin foto
bersama, mendengarkan uraiannya, juga mendapatkan pencerahan dari
kalimat-kalimatnya yang sederhana, namun terasa mengalir dan menyesap dalam
jiwa. Orang-orang berharap untuk menjalani garis nasib sebagaimana Afrial.
Minimal bisa memiliki semangat hebat sebagaimana ditunjukkan Afrial. Saat
memulai pertemuan itu, Afrial langsung berpantun:
Masak air biar mateng
Tukang
balon deket banner
Saya
ucapkan selamat dateng
buat
anda calon milyader
Afrial memang seorang milyader yang diharapkan
berbagi motivasi dan semangat. Namun orang-orang berkumpul bukan karena fakta
dirinya seorang milyader. Orang-orang berdatangan karena kisah dan perjuangan
Afrial menuju ke titik itu dilalui dengan “berdarah-darah.” Bukan soal siapa
dia sekarang yang penting, melainkan bagaimana dirinya bekerja keras dan
melakukan segala upaya untuk tiba di titik itu.
Kisahnya yang memulai segala sesuatu dari
nol adalah sungai inspirasi yang tak pernah mengering. Mereka yang hadir di
pertemuan itu berharap bisa mengikuti jejak Afrial. Dalam banyak kesempatan,
Afrial selalu meyakinkan orang-orang bahwa menjadi milyader itu bukanlah mimpi
di siang bolong. Semuanya bisa digapai, sepanjang ada usaha dan niat yang kuat.
Mereka yang hadir di pertemuan itu adalah
mereka yang memiliki harapan kuat untuk hidup yang lebih baik, dan lebih
bermanfaat bagi sekitarnya. Kisah dan filosofi hidup Afrial diharapkan bisa melecut
orang lain untuk bangkit dan segera keluar dari kehidupan yang biasa saja. Ia
menyapa semua orang sebagai milyader demi memotivasi mereka bahwa dalam keadaan
sesusah apapun, semua orang harus punya harapan. Orang-orang harus optimis
untuk menggapai mimpinya, sebab mimpi ibarat kompas untuk menggapai masa depan.
Setidaknya, Afrial telah membuktikan itu melalui pengalamannya.
Kisahnya serupa kisah dari negeri dongeng
yang menjadi kenyataan. Kisahnya serupa mimpi yang menjadi kenyataan dalam
waktu singkat. Dahulu, ia hanyalah seorang kondektur bus yang setiap hari
berpeluh di terminal. Ia bekerja di bus PPD trayek Grogol-Kampung Melayu 213. Ia
merasakan bagaimana berteriak memanggil penumpang, menagih ongkos bus ke
penumpang, setelah itu berdiri di pintu bis yang setiap saat terkena panas
matahari.
 |
| Quick Facts Afrial Tabrani |
Akan tetapi, hanya dalam waktu dua tahun
lebih, ia bertransformasi, dari seorang kondektur bus dengan penghasilan
pas-pasan, menjadi seorang milyader
dengan penghasilan di atas 300 juta rupiah sebulan. Ia melampaui apa yang
dianggap banyak orang sebagai kemustahilan. Ia mengubah dirinya, dari lelaki
yang setiap hari berada di pintu bus sembari menagih pembayaran ke penumpang,
menjadi seorang pemilik mobil Mercy dua pintu seri terbaru.
Afrial melampaui hal-hal yang tak bisa
dibayangkan banyak orang. Dari sosok yang tadinya didera kemiskinan, menjadi
sosok baru yang berlimpah kemewahan. Dari sosok yang rumahnya kontrakan dan
dibayar dengan cara menabung di celengan, menjadi sosok yang memiliki rumah di
kompleks perumahan mewah, punya banyak apartemen, serta aset di mana-mana. Dari
sosok yang tadinya bekerja keras setiap hari demi segenggam rupiah, menjadi
sosok yang tak perlu bekerja keras, namun aset dan kekayaannya terus membesar.
Dari sosok yang tadinya adalah kernet bus dengan 12 jendela, menjadi sosok
pemilik mobil Mercedes dua pintu senilai miliaran rupiah.
Dahulu ia hanya bisa membayangkan seperti
apa rasanya liburan. Kini, ia bisa keliling Eropa dan mengunjungi pusat
peradaban di banyak tempat. Di banyak tempat di Eropa, ia sengaja memakai pakaian
khas Betawi, sebagai simbol identitas dan komunitasnya. Sampai kapanpun, ia
tetap bangga sebagai orang Betawi yang akhirya sukses menggapai kekayaan. Ia
mengikuti jejak legenda Betawi, Benyamin Sueb, yang dahulunya seorang sopir
terminal hingga menjadi entertain legendaris di Indonesia. Bedanya, Afrial
menggapai mimpinya melalui bisnis yang dikerjakan hanya dengan modal nekad dan
keberanian.
Sosok Afrial memang unik. Banyak orang
yang menggapai puncak kekayaan, namun harus dibayar dengan jam kerja sibuk
serta tiadanya waktu untuk keluarga. Sementara Afrial tak perlu harus bekerja
keras di kantoran sebagaimana kebanyakan orang. Ia cukup duduk di rumah,
berlibur di hotel, atau bersenang-senang bersama keluarga. Ia menggapai apa
yang disebut kebebasan finansial itu pada usia 40 tahun, usia yang relatif
muda. Dengan waktu luang yang besar, ia bisa berbuat banyak kepada keluarga,
menjadi gerbong yang menarik kehidupan ayah ibu dan keluarganya menjadi lebih
baik, juga membagikan pengalamannya kepada banyak orang.
Kehadiran Afrial di ajang BOM itu adalah
bagian dari ikhtiarnya untuk membagikan pengalaman. “Sejatinya, mental kaya adalah ketika bahagia bukan lagi karena
mendapatkan, melainkan karena memberi dan membagi-bagikan.” Ia ingin agar
banyak orang bisa mengikuti jejaknya. Ia tak ingin kaya seorang diri. Ia ingin
mengajak sebanyak-banyaknya orang lain untuk keluar dari zona nyamannya, lalu
menggapai sukses sebagaimana dirinya
Presentasinya selalu menarik dan
dinanti-nanti. Dikarenakan berasal dari masyarakat kebanyakan, yang terbiasa
bergelut dengan problem ekonomi, kalimat-kalimat dalam setiap presentasinya
selalu membumi. Bahasanya tak melangit ala kelas menengah perkotaan yang susah
dipahami. Afrial selalu memilih bahasa yang sederhana, yang bisa dipahami siapa
saja. Apapun profesi anda dan apapun pendidikan anda, dijamin akan memahami apa
yang dikatakan Afrial. Ia juga pandai memilih diksi yang jenaka, tapi tetap
sarat makna. Misalnya saat mengatakan: “Orang
sering bilang kaya itu ujian. Tapi jangan salah, miskin juga ujian. Kalau
memang sama-sama ujian, mending pilih kaya aja deh.”
Dalam setiap presentasinya, ia
menyampaikan dalam aksesn Betawi yang khas. Ia juga jenaka dan bisa membuat
semua orang terpingkal-pingkal. Presentasi Afrial bukan sesuatu yang serius dan
membosankan. Ia bisa mengubah suasana forum menjadi snatai, ceria, serta
menyenangkan. Ia punya orisinalitas, sesuatu yang diinginkan oleh semua
pemateri.
Biarpun lahir dari keluarga pas-pasan, ia
tak lantas mengutuki keadaan. Ia tak hendak menyalahkan apapun di sekitarnya. Kekuatan
Afrial adalah keberanian untuk menjelajah di luar zona nyaman. Ia percaya bahwa
“Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik
jika kita menyalakan sebatang lilin.” Lilin yang dinyalakannya itu adalah
berbagai upaya untuk keluar dari keadaan miskin yang dirasakannya sejak kecil.
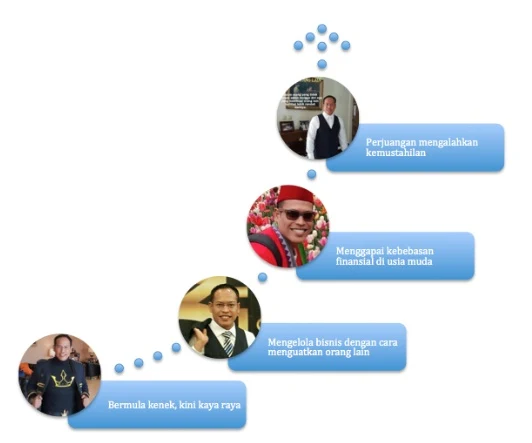 |
| Quick Facts Afrial Tabrani (2) |
Ia membaca buku Berani Gagal yang ditulis Billi PS Lim yang mengisahkan seorang
warga miskin di Singapura yang berhasil menjadi jutawan karena keberaniannya
menghadapi semua kegagalan, lalu mengubahnya menjadi kesuksesan. Ia juga
membaca buku yang ditulis Napoleon Hill tentang bagaimana membangkitkan
kekuatan dahsyat dalam diri setiap orang. Ia lalu bekerja keras sembari
menemukan bagaimana kiat untuk keluar dari garis kemiskinan. Ia mengatakan, “Jika anda terlahir miskin, maka itu bukan
salah anda. Namun jika anda meninggal dalam keadaan miskin, berarti ada sesuatu
yang salah pada diri anda.”
Pada kesempatan lain, ia juga mengatakan, “Saya memang lahir dari keturunan miskin.
Tapi saya bertekad kemiskinan hanya boleh sampai di saya. Tidak boleh di
generasi anak-anak saya.”
Jika kita menyimak sejarah, semua orang
besar selalu melalui jalan yang tidak mudah. Mereka biasanya mengalami masa
kecil yang tidak istimewa, lalu secara perlahan-lahan mulai mengembangkan
dirinya hingga mencapai posisi politik tertentu. Semua penderitaan dan
perjuangan itu menjadi pembelajaran berharga untuk bangkit dan keluar sebagai
pemenang.
Presiden Amerika, Theodore Roosevelt,
mengalami masa kecil yang sakit-sakitan. Sejak kecil, berbagai penyakit mendera
tubuhnya sehingga keluarganya sibuk membawanya ke berbagai tempat untuk terapi.
Dia juga menderita rabun jauh sehingga mengganggu proses belajarnya. Hingga
suatu hari ayahnya berbisik, “Percuma kau belajar keras kalau tubuhmu rapuh.
Kendaraan pribadimu yang lemah itu tidak akan pernah bisa membawamu ke masa
depan yang kau impikan lewat sekolah,” katanya.
Kalimat itu menjadi cambuk baginya. Ia
lalu melatih fisiknya, mengatasi ketidakmampuannya melihat jauh dengan memakai
kacamata tebal, lalu menekuni banyak cabang olahraga. Berkat kerja kerasnya di
berbagai bidang, ia melebarkan sayap ke dunia politik. Ia menghadapi banyak
tantangan, hingga akhirnya disumpah sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun
1901. Ia menjadi presiden termuda dalam sejarah Amerika, yakni 42 tahun. Tak
hanya menjadi presiden termuda, ia juga seorang sejarawan terkemuka,
penjelajah, peraih nobel perdamaian, dan ahli lingkungan yang tak tertandingi.
Nasib serupa juga bisa dilihat pada sosok
Soekarno. Sejak usai belia, ia sudah terbiasa mandiri dan lepas dari
bayang-bayang orangtua.Ia bukan tipe anak manja yang tinggal di rumah untuk
belajar di bawah pengawasan orangtua. Ia mencari tantangan, dengan berangkat ke
kota lain untuk belajar lalu tinggal di rumah tokoh besar Tjokroaminoto. Bahkan
ketika menjadi insinyur, ia menempuh risiko dengan mendedikasikan dirinya untuk
perjuangan memerdekakan Indonesia, negeri yang dahulu hanya bisa dibayangkannya.
Banyak tokoh besar melalui masa mudanya
dengan kemandirian, kerja keras, serta tak lupa menganyam mimpi-mimpi besar.
Orang-orang besar memikirkan masa depan, melalui langkah-langkah kecil yang
penuh risiko di masa kini. Mereka meletakkan imajinasinya sebagai cahaya yang
menuntun perjalanan. Mereka menjadikan satu mimpi sebagai titik akhir, setelah
itu menyusun langkah demi langkah untuk memenangkan masa kini.
Kita bisa melihat kerja keras dan upaya
menempa diri itu pada Afrial Tabrani. Selama tiga generasi, keluarga Afrial
bekerja di terminal. Mulai dari kakek, ayah, hingga dirinya. Pekerjaan mereka
tak jauh-jauh dari supir dan kenek. Profesi ini dilakoni secara turun-temurun.
Sejak SMP, ia menempa dirinya untuk mandiri. Ia menjalani banyak profesi, mulai
dari pekerja di supermarket, tukang bangunan, calo di percetakan, hingga
bekerja memasarkan multi-level.
Dalam segala kesulitan hidup, ia tetap
memelihara impian, dan berusaha keras untuk menggapainya. Baginya, lebih baik
mati dalam berusaha menjadi orang sukses, ketimbang berjuang dan hanya hidup
sia-sia. Banyak orang yang mengatakan bahwa impian tak perlu mimpi setinggi
langit, sebab jika jatuh, maka pasti akan sakit. Padahal, justru melalui mimpi
itulah seseorang bisa menemukan peta hidup khususnya mengenai seberapa besar
kerja keras yang akan dilakukannya. Melalui mimpi itu, orang-orang akan
menemukan kekuatannya.
Bagi Afrial, mereka yang sukses adalah
mereka yang berani bermimpi besar. “Orang sukses adalah orang yang menjiwai
impiannya. Jangan cuma tulis di status. Jiwai. Masukkan ke alam bawah saadar.
Impian itu harus besar. Jangan takut impian hal-hal besar,” katanya. Daripada
sibuk memikirkan apa yang dikatakan orang, jauh lebih penting memikirkan apa
saja yang sudah dilakukan untuk menggapai impian. Tanpa kerja keras, mimpi
hanya akan tertinggal sebagai mimpi. Tapi siapapun yang bekerja keras dan fokus
mengejar impiannya, maka segala kemustahilan akan lenyap. Mimpi tanpa usaha
adalah kesia-siaan, tapi mimpi yang diimbangi kerja keras dan berdoa adalah
kekuatan yang bisa mengalahkan apapun.
Dari dulu saya punya prinsip lebih baik mati dalam mencoba berusaha jadi orang sukses ketimbang saya tdk berjuang dan hanya hidup biasa-2 aja.. Dan selama proses perjuangan itu saya sering mendengar apakah itu teman saya,saudara saya atau orang lain yg mengatakan : Yal, kalo ngomong jgn gede-2..tau diri dikit lah. Atau : Yal, kalo ngimpi jgn tinggi-2..ntar kalo nggak kesampean bisa jatuh sakit.. Atau lebih parah lagi..sy suka di bilang hubbud duunya, orang yg terlalu cinta kepada dunia..Tp saya tdk pernah memperdulikan pendapat itu.. Dan sy juga tdk mendebat nya..Krn prinsip saya, apapun yg keluar dari mulut orang lain adalah benar, kebenaran menurut versi mereka..Tetapi pada kenyataan nya, hari ini..Alhamdulillah prinsip saya benar..Dan akhir nya mereka terpaksa mengeluarkan kalimat pamungkas nya : Aach, itu mah emang udah rezeki loe aje Yal..Masya Allah..#KitaKIM
#KitaPunyaPrinsip
Mimpi sukses Afrial itu perlan-pelan
terbentang saat dirinya diperkenalkan dengan 3i Networks yang berada di bawah
naungan PT AJ Central Asia Raya (CAR) yang dimiliki Salim Grup. Ia melihatnya
sebagai peluang baru untuk keluar dari roda kemiskinan yang telah menimpa
keluarganya selama tiga generasi. Ia memutuskan untuk bergabung sembari menanam
harapan bahwa dirinya akan sukses menggapai mimpinya.
CAR telah eksis selama 41 tahun dan telah
melalui berbagai macam kondisi perekonomian baik dalam negeri maupun secara
global. Perusahaan ini kian kokoh dan kuat seiring waktu. Pada awal tahun 2014, CARLife Insurence
membuka kemitraan untuk nasabah dengan nama "3i-Networks". Dengan 3
manfaat dasar yang sangat penting dan menjadi trend setter, yakni (1) asuransi,
(2) investasi, (3) income atau penghasilan. Inilah kekuatan 3iNetworks yang
tidak ditemukan di produk perbankan.
Dengan sistem pemasaran melalui "Networks Marketing," yang membuka peluang emas yang bernas dan berkelas; tanpa modal, tanpa gagal, tanpa resiko, mudah dijalankan dan potensi karier juga ladang penghasilan yang luar biasa. Orang-orang cukup menabung sesuai penghasilan, yakni 350 ribu, 700 ribu atau 1 juta rupiah sebulan. Selain menabung, bisa pula mereferensi teman untuk bergabung. Model bisnis di 3iNetwork terbilang sederhana dan mudah dilakukan siapa saja.
Hanya dengan menabung sebesar 350 ribu
rupiah selama lima tahun di CAR, potensi keuntungan bisa didapatkan hingga umur
74 tahun. Cukup menabung lima tahun, maka tahun ke-6 dan seterusnya, seseorang
bisa mendapat keuntungan besar jika berhasil mengelola jaringan menjadi luas. Tak
sekadar tabungan, CAR juga memiliki manfaat asuransi. Jika pemilik tabungan
meninggal, maka keluarga akan mendapatkan dana yang cukup besar sebagai warisan.
Nilai lebih CAR yang menjadi keinginan besar banyak orang adanya kesempatan
untuk mendapatkan penghasilan tambahan, dengan cara mengajak orang lain untuk
bergabung di situ.
Afrial menjelma sebagai meteor di bisnis
jaringan ini. Ia yang sebelumnya jatuh bangun di bisnis multi-level, melihat
cahaya terang di bisnis ini. Ia melihat bisnis ini bukan multi-level, juga
bukan murni asuransi. Bisnis ini mendidik orang-orang agar memiliki tabungan,
yang kelak akan bisa menjamin masa depan orang lain. Setelah dikalkulasinya,
tak ada sediitpun rugi bergabung di bisnis ini. Skenario yang dihadapi hanya
dua: kaya dan super kaya. Optimismenya membumbung tinggi saat dijelaskan
mengenai peluang-peluang yang bisa didapatnya di bisnis ini.
Biarpun hidupnya terbilang miskin, ia
berhasrat kuat untuk keluar dari zona itu. Segala kesusahan dan
penderitaandilihatnya sebagai tantangan. Ia sering mengutip kalimat dalam film
American Gangster, “Hidup ini bukan
tentang seberapa keras kau memukul, tapi seberapa keras pukulan yang kau terima
dan terus maju. Berapa banyak pukulan yang bisa kau terima, dan terus bergerak
maju. Begitulah kemenangan diraih.”
Dalam kondisi yang penuh tantangan, Afrial
selalu bangkit dan melangkah ke depan. Satu kebahagiaan yang didapatnya dari
3iNetworks adalah bisnis ini menekankan pada tabungan, sehingga semua orang
yang bergabung di dalamnya pasti akan mendapat keuntungan. Minimal, orang-orang
bisa memiliki tabungan, serta bisa memenuhi banyak kebutuhan. Model bisnis
3iNetworks menekankan pada pentingnya membangun jejaring serta pelunya saling
menguatkan.
Berkat mental yang tahan banting, Afrial
mulai bangkit. Dalam waktu dua tahun lebih, ia sukses menggapai banyak posisi,
hingga akhirnya mencapai puncak yakni Crown, dengan taksiran penghasilan hingga
300 juta rupiah dalam sebulan. Penghasilan ini setara dengan penghasilan
seorang direktur industri pertambangan. Padahal direktur perusahaan tambang
membutuhkan puluhan tahun, serta jenjang karier yang panjang untuk sampai pada
posisinya. Belum lagi jam kerja tinggi yang harus dijalani seorang direktur. Sementara
Afrial hanya membutuhkan waktu singkat, tidak mengeluarkan modal besar, serta
memiliki waktu luang yang besar.
***
POHON-pohon rindang menyambut siapapun
yang hendak berkunjung ke Perumahan Alam Sutera. Suasana asri dan sejuk segera
terasa saat memasuki kompleks perumahan yang banyak dihuni oleh warga dengan
kemampuan ekonomi di atas rata-rata. Untuk memasuki setiap kompleks,
orang-orang mesti melewati pos security
yang akan meminta identitas serta menyakan keperluan.
Di salah satu kompleks perumahan, Afrial
tinggal bersama istri dan anaknya. Ia mudah ditemui pada saat tidak sedang
keluar kota. Cukup menyampaikan pada security, selanjutnya diberi akses ke
rumah Afrial. Biasanya, pihak security akan membuntuti tamu yang datang demi
memastikan tamu tersebut dikenali dan bersedia ditemui oleh Afrial.
Di depan rumah Afrial terdapat mobil bermerk
Mercedes Benz S Class Coupe yang memiliki dua pintu. Di pasaran, harga mobil
terbaru Mercy ini sekitar 2,23 miliar rupiah. Di kap mobil itu terdapat logo
serupa mahkota berwarna kuning keemasan, bertuliskan KIM.
Masih di depan rumah itu, terdapat satu
motor matic jenis Mio yang diposisikan seperti monumen. Siapapun yang
berkunjung akan sama-sama memahami bahwa motor itu adalah motor bersejarah yang
dahulu menemani Afrial semasa masih mengejar kesuksesan. Motor itu hadir dalam
banyak momen-momen sulit, juga mengantarnya hingga akhirnya berada pada titik
seperti sekarang ini. Motor itu adalah saksi masa-masa susah hingga masa-masa
penuh kegembiraan.
 |
| Afrial semasa berjuang |
Dalam satu presentasi, Afrial
membandingkan motor itu dengan mobil mercy dua pintu yang dipunyainya sekarang.
Motor itu harusnya dikendarai dua orang, tapi dipakai bertiga yakni Afrial dan
dua anaknya. Sementara mobil mercy, harusnya dikendarai oleh dua orang, tapi
tetap saja dipakai bertiga. Tentu saja, yang membedakan adalah kualitas dan
harga kedua kendaraan tersebut.
Ruangan di dalam rumah itu dibuat lebih
adem. Interiornya banyak dipenuhi gambar Afrial dan istrinya, Suhartini. Foto
mereka berdua dibuat seperti poster film sehingga nampak cantik. Ada poster
yang menampilkan mereka berdua dalam pakaian Kaisar Cina. Ada juga beberapa
poster yang meniru film Hollywood. Kata Afrial, poster-poster itu dibuat saat
dirinya hendak menikah. Di gedung tempat resepsi pernikahan, foto-foto itu
menjadi aksesoris yang bisa dilihat banyak orang.
Rumah itu adalah hasil kerja kerasnya
selama dua tahun terakhir. Sebelumnya, ia telah menggapai salah satu mimpinya
yakni membelikan rumah untuk orangtuanya. Rumah di Perumahan Alam Sutera ity
menjadi tempat bermukim keluarganya. Ia juga memiliki beberapa kendaraan mewah,
lima apartemen, serta aset yang tersebar di banyak titik. Sebagai peraih crown,
ia juga memiliki penghasilan hingga 300 juta rupiah sebulan.
Banyak orang yang menggapai sukses, tetapi
harus dibayar dengan hilangnya waktu bersama keluarga. Hari-hari dihabiskan
dengan bekerja keras, tanpa memikirkan bagaimana nasib keluarga. Afrial berbeda
dengan mereka. Ia sukses secara finansial, tapi memiliki waktu yang lebh banyak
luangnya. Pada saat orang-orang sibuk bekerja, ia justru liburan dan bersantai
di rumahnya. Mereka yang pernah ke rumahnya, pasti paham bahwa seringkali
Afrial malah tidur siang, pada saat orang lain sedang sibuk bekerja.
Afrial telah mencapai apa yang disebut
Robert Kiyosaki sebagai “kebebasan finansial.” Ia tak perlu harus bekerja lagi
sebagaimana orang-orang yang mengejar gaji bulanan agar punya penghasilan. Ia
bisa menikmati harinya dengan berlibur dan bersantai sebab dirinya akan tetap
mendapat pemasukan setiap saat. Sebagai network marketing, ia membangun sistem
yang lalu bekerja untuk dirinya, juga menjamin kehidupannya bersama keluarga,
tanpa harus banting tulang lagi.
Analogi yang tepat untuk ini adalah
perbandingan cicak dan laba-laba. Cicak adalah gambaran orang yang selalu
keluar rumah untuk mencari makan. Cicak memang bekerja keras tapi hasilnya
hanya cukup untuk dimakan sehari. Keesokan harinya, dia akan keluar rumah lagi
demi mencari makan. Sementara laba-laba bekerja keras hanya saat membangun
jaring. Setelah jaring itu terbentuk, ia tinggal duduk diam di tengah, lalu
menunggu serangga yang berhasil dijaring. Ia hanya bermodalkan jaring untuk
menangkap mangsa.
 |
| belajar pada Afrial |
Manusia tipe cicak adalah manusia yang
bekerja keras, tanpa membuat perencanaan yang matang. Pada satu masa, fisik
manusia tipe cicak akan berkurang sehingga dirinya kelak akan kehilangan
kemampuan bekerja. Pada titik ini, dia akan menjadi beban bagi sekelilingnya
sebab tidak lagi seproduktif dulu. Sementara manusia tipe laba-laba berhasil
membangun sistem sehingga bisa berkonsentrasi untuk melakukan pekerjaan lain,
saat kebutuhan finansialnya terpenuhi. Manusia tipe laba-laba hanya banting
tulang saat membangun sarang, setelah itu bisa duduk manis sebab sarang itu
akan menangkap banyak serangga.
Ketika kebebabsan finansial berada dalam
genggaman, Afrial bisa merencanakan waktu yang berkualitas, bersama keluarga
kecilnya. Tak hanya itu, ia juga berbagi ilmu dan pengetahuan dengan
orang-orang lain agar banyak orang bisa sesukses dirinya. Ia menyediakan waktu
yang luas bagi siapapun yang hendak silaturahmi di rumahnya.
Di rumah yang terletak di Perumahan Alam
Sutera itu, itu, Afrial memulai hari. Rumah itu seringkali dikunjungi oleh
mitra-mitranya yang selama ini dibantu dan dibesarkannya. Setelah menggapai
sukses, ia mulai menularkan kesuksesan itu kepada orang lain. Ia berbagi
pengalaman dan pengetahuan agar orang lain bisa menggapai sukses sebagaimana
dirinya. Ia sadar benar bahwa kesuksesan
bukanlah kerja seorang diri, tapi ada bantuan banyak orang. Ia ingin agar
banyak orang bisa mengikuti jejaknya.
Dalam buku Outliers, yang pertama kali terbit tahun 1988, Malcolm Gladwell
mengatakan bahwa kesuksesan tidak berasal dari angka nol. Semua orang berutang
pada orang tua dan dukungan orang lain. Kesuksesan adalah apa yang sering
disebut oleh para sosiolog sebagai “keuntungan yang terakumulasi”. Tempat dan
kapan seseorang tumbuh besar memiliki pengaruh yang cukup besar.
Gladwell menolak anggapan tentang keberhasilan yang semata-mata dipicu oleh kecerdasan. Menurutnya, keberhasilan seseorang menggapai satu kesuksesan tidak bisa dilihat hanya dari satu aspek saja, melainkan terdapat hal yang lebih rumit, kompleks, dan hanya bisa dipahami dengan menelusuri kehidupan orang tersebut.
Gambaran yang paling sederhana namun
gamblang dipaparkan Malcolm Gladwell dalam cerita singkat mengenai pohon. Pohon
ek tertinggi di hutan menjadi yang tertinggi bukan semata-mata karena dia
paling gigih. Dia menjadi yang tertinggi karena “kebetulan” tidak ada pohon
lain yang menghalangi sinar matahari kepadanya, tanah di sekelilingnya dalam
dan subur, tidak ada kelinci yang mengunyah kulit kayunya sewaktu masih kecil,
dan tidak ada tukang kayu yang menebangnya sebelum dia tumbuh dewasa. Dukungan
lingkungan adalah hal yang sangat ditekankan oleh Gladwell.
Melalui jaringan 3iNetworks, Afrial
menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dengan banyak orang.
Rahasia kesuksesannya terletak pada kerja keras, kemampuan melihat peluang
serta dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Ketika ditanya rahasia sukses,
ia hanya menjawab singkat, “Kesuksesan itu digapai oleh orang yang menunda
kesenangan, berani keluar dari zona nyaman, dan tetap optimis pada saat orang
lain pesimis.”
Seringkali saya ditanya apa rahasia sukses?Saya jawab, pada dasarnya tidak ada rahasiaRata-2 orang sudah tahu cara menjadi sukses, hanya saja kebanyakan dari mereka tidak melakukan apa yg mereka ketahui tsbSangat sederhana, tidak ada rahasiaMenunda kesenangan, keluar dari zona nyamanTetap optimis saat yang lain sedang pesimisBekerja ekstra saat yang lain bersantaiBelajar dari kesalahan saat yang lain mengeluhDisiplin dan konsisten mengikuti aturan main saat yang lain bebal dan tak peduliSelalu produktif saat yang lain buang-buang waktuBerpikir dan berjiwa besar saat yg lain menolak dan meremehkanTetap bertahan saat yang lain berhentiDan Anda akan menang saat yang lain kalahGo Crown !!#KitaKIM29 Mei 2017
Biarpun sebagian besar impinya telah
tercapai, ia tetap menantang dirinya untuk mencapai hal lain. Tantangan akan
membuat hidupnya bergairah. Pernah, seseorang berseloroh bahwa ketika kaya,
maka tidak ada lagi mimpi yang harus digapai. Afrial spontan menjawab, “Kalau
gak ada mimpi lagi, berarti kamu udahjadi mayat hidup. Yang namanya manusia,
pasti ada yang mau dikejar.”
***
BUKU ini tak saja menyajikan kisah hidup
Afrial Tabrani, seorang kenek bus yang sukses menjadi milyader hanya dalam
waktu 2,5 tahun. Buku ini menyajikan keping-keping impian dari seorang lelaki
Betawi yang berani keluar dari zona kemustahilan. Berkat keberanian untuk
bermimpi itu, Afrial merengkuh kehidupan yang sebelumnya tidak berani
dimimpikan banyak orang.
Dalam hidup, banyak orang yang membatasi
impiannya, atau barangkali takut untuk sekadar bermimpi. Banyak yang takut akan
jatuh dalam upaya mengejar mimpi itu, Tapi Afrial justru berani berkhayal dan
bermimpi setinggi-tingginya. Mimpi itu menjadi kompas yang memandu semua langkah-langkahnya
untuk menggapai hasil yang maksimal. Mimpi itu menjadi cahaya lilin yang
mengatasi pekatnya malam.
Biarpun hari ini ia bukan lagi kenek bus,
melainkan telah menjadi milyader, ia tetap Afrial yang mau berbagi sukses
dengan siapa saja. Dengan senang hati, ia berbagi pengalaman dengan siapapun
agar sukses di dunia network marketing, sebagaimana dirinya. Ia percaya bahwa
dengan berbagi kiat sukses, strategi, dan mimpi, maka semua orang bisa keluar
dari zona nyaman lalu menggapai kebebasan finansial. Ia percaya bahwa semua
orang bisa menggapi hidup yang lebih bahagia dan berkualitas.
Buku ini juga menyajikan kiat-kiat praktis
bagi mereka yang hendak brkecimpung di dunia yang sama dengan Afrual, yakni
dunia network marketing atau pemasaran berjejaring. Bergabung di 3iNetwork,
Afrial sukses memaksimalkan modal yang sekecil-kecilnya demi menggapai hasil
yang sebesar-besarnya.
Pesan yang hendak disampaikan dalam buku
ini adalah semua orang bisa menggapai sukses, bisa menjadi kaya, bisa membawa
manfaat bagi sesamanya. Tak peduli apa latar belakang seseroang, kesuksesan
bisa menjadi milik semua orang, sepanjag orang itu bisa berusaha bagi dirinya
demi mengubah keadaannya. Persis, sebagaimana dikatakan Afrial:
Semakin lama menunda, semakin jauh tertinggal...Semakin sering bersantai, semakin lama membuktikan...Stop menawarkan kesuksesan jika diri sendiri masih penuh kegalauan...Sadari, orang2 di sekitar sedang memperhatikanmu...Sadari lebaran ini keluargamu di kampung mendoakanmu agar jadi orang suksesSo..Semakin lama engkau menunjukkan hasil maka akan semakin berat langkah2mu...!Maka... Segera bereskan keraguan dirimu, dan mulailah berlari dengan kecepatan penuh habis Lebaran ini !Tunjukkan bahwa kau layak di banggakan keluargamu.#3iNetworksCAR#KitaKIM. 24 Juni 2017


