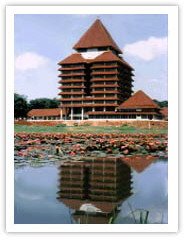KONSEP Lingkar Hermeneutik Paul Ricoeur mendapatkan inspirasi dari konsep yang dikemukakan dua filsuf Jerman yaitu Imanuel Kant (1724-1804) dan Georg Willem Hegel (1770-1831). Ricoeur menggabungkan konsep logika Kant dan konsep dialektika Hegel untuk merumuskan konsep Lingkar Hermeneutik.
Kant memaparkan konsep tentang logika kritis sebagai bentuk kritikan terhadap rasionalitas manusia modern. Dalam karyanya Critique of Pure Reason (1781), ia memaparkan basis epistemologi pengalaman manusia. Menurutnya, pengetahuan senantiasa bergerak dari hal yang sifatnya empiris (dapat diindrai) dan rasional hingga tahapan rasio kritis di mana pikiran manusia membentuk kategori-kategori yang sifatnya apriori. Kant membedakan antara pengetahuan empiris dan apriori. Jika pengetahuan empiris berdasarkan pada persepsi atau pengalaman, maka apriori justru berkembang dalam pikiran manusia sebagai sintesis dari beberapa ide atau konsep tentang sesuatu. Kant menyebut epistemologi kritis bisa membantu perkembangan ilmu pengetahuan.
Sedangkan konsep Hegel tentang dialektika adalah upaya untuk menemukan kebenaran filosofis melalui perbenturan atau konfrontasi antara satu gagasan (tesa) dengan gagasan lainnya (antitesa) hingga melahirkan sintesa. Sebelum Hegel, gagasan dialektika sudah ada dalam karya filsuf Yunani kuno Plato yaitu Dialogues. Dialektika juga ditemukan dalam catatan-catatan Aristoteles yang hendak mencari dasar filosofis ilmu pengetahuan dan menggunakan istilah dialektika sebagai sinonim dari logika ilmu. Hanya saja, Hegel justru menjadi pihak yang lebih dikenal publik sebagai filsuf yang menjadikan dialektika sebagai inti pandangan filsafatnya.
Dalam pahaman Hegel, gagasan atau ide berkembang melalui proses yang sifatnya dialektis. Sebuah konsep akan berhadapan dengan antitesis konsep itu hingga melahirkan sintesis yang merupakan titik tengah dari konfrontasi tersebut. Baginya, sintesa berada pada level yang lebih tinggi dari tesa dan antitesa.
Ricoeur menggabungkan logika Kant dan dialektika Hegel untuk mengembangkan teori tentang interpretasi. Ricoeur menghilangkan aspek sintesa dalam dialektika Hegel. Menurutnya, sintesa tidak akan pernah lahir sebab dialektika adalah sebuah proses yang tidak akan pernah berkesudahan. Gagasan dialektika Ricoeur inilah yang kemudian disebut sebagai Lingkar Hermeneutik dalam studi tentang penafsiran.
Lingkar Hermeneutik Menurut Schleiermacher dan Dilthey
Filsuf Jerman Friedrich Schleiermacher (1768-1834) menjadi tokoh pembaharu yang memposisikan hermeneutik sebagai metode umum untuk segala sesuatu. Ia mendefinisikan Lingkar Hermeneutik sebagai upaya untuk menafsirkan sesuatu melalui dialektika antara gramatikal dan teknis psikologis. Gramatikal adalah memahami makna satu kata dengan cara menempatkannya pada konteks kata yang lain. Sebuah kalimat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh kata. Makna sebuah kata dipahami dengan melihat kalimat atau relasinya dengan kata yang lain. Demikian pula sebaliknya, makna sebuah kalimat bergantung pada makna kata dalam kesatuan tersebut. Interaksi dialektis antara keseluruhan dan bagian itu memberikan makna yang lain. Inilah yang disebut sebagai Lingkar Hermeneutik. Kata Schleiermacher, makna gramatikal berupa makna proposisi atau makna yang sudah dibakukan oleh konvensi sosial.
Sedangkan teknis psikologis berkaitan dengan konteks psikologis dari seorang pengarang ketika mengarang sesuatu. Ini juga mencakup maksud pengarang yang ditentukan oleh intensi atau sesuatu yang berasal dari dalam dirinya.
Senada dengan gagasan Schleiermacher, filsuf Jerman Wilhelm Dilthey (1833-1911) menjadi tokoh yang juga menorehkan tinta emas dalam pengembangan teori hermeneutika. Dilthey hidup pada masa ketika filsafat idealisme Hegel sedang jatuh dan ditumbangkan oleh positivisme. Pemikiran ilmu alam yang ditandai metode erklaren (eksplanasi) menjadi pemikiran yang mendominasi seluruh bangunan ilmiah. Dilthey lalu mengembangkan pemikiran tentang verstehen (understanding) sebagai bentuk gugatan pada ilmu yang terlampau positivistik. Verstehen dilahirkan dalam bingkai kritik sejarah dan ikhtiar memunculkan human science.
Dilthey juga menjelaskan tentang Lingkar Hermeneutik secara rinci. Menurutnya, Lingkar Hermeneutik terdiri atas:
- Hubungan melingkar antara Part (sebagian) dan whole (keseluruhan)
Lingkar Hermeneutik adalah dialektika atau perputaran antara part (bagian) dan whole (keseluruhan) dalam memahami sesuatu. Part secara sederhana bisa didefinisikan sebagai makna kata secara tunggal. Makna kata secara denotasi (sebenarnya). Misalnya, kata Ambon bermakna nama identitas kota yang terletak di Kepulauan Maluku. Sedangkan whole (keseluruhan) adalah melihat makna kata dalam relasinya dengan kata-kata yang lain dalam satu struktur kalimat. Misalnya kalimat,”Saya makan pisang ambon”. Kata Ambon langsung memiliki makna yang berbeda ketika ditempatkan dalam konteks kalimat.
- Lingkar antara Ends dan Means
Ends adalah tujuan sedangkan means adalah makna. Maksudnya adalah setiap tindakan manusia pasti mempunyai tujuan. Naluri yang ada pada diri manusia adalah memiliki arah serta tujuan ke mana hendak bergerak. Demi mencapai tujuan itu, manusia mengembangkan sejumlah strategi atau teknik.
- Lingkar di antara inner dan outer.
Inner adalah sesuatu yang ada dalam diri manusia baik itu menyangkut pikiran, perasaan, serta persepsi akan sesuatu. Sedangkan Outer adalah apa yang ada di luar diri manusia berupa tindakan, serta ekspresi yang dipancarkan seseorang. Lingkaran Inner dan Outer adalah ketegangan antara apa yang ada dalam diri dan apa yang diekspresikan. Ketegangan antara ekspresi dan mental state. Contoh dari lingkaran di antara inner dan outer ini adalah konsep tentang orang Jawa. Apakah memahami konsep orang Jawa berdasarkan nilai yang ada dalam dirinya ataukah memahami nilai melalui ekspresi dan mental state. Contoh lain adalah apakah seseorang memahami bahasa akan membawanya pada pemahaman akan makna ataukah pemahaman akan makna yang kemudian membawanya pada pemahaman akan bahasa.
- Kekuasaan
Setiap tindakan manusia akan dipahami jika mempunyai sifat menguasai (affecting) atau dikuasai (being affected). Contohnya adalah pertanyaan apakah kebudayaan Jawa yang membentuk manusia Jawa ataukah manusia Jawa yang membentuk kebudayaan Jawa. Di Indonesia, isu ini menjadi isu yang demikian penting sebagaimana terlihat pada polemik tentang posisi manusia Indonesia antara Sutan Takdir Alisjahbana dengan Ki Hadjar Dewantara dan Tjipto Mangunkusumo. Demikian pula polemik kebudayaan yang memperhadapkan penganut sastra realisme sosialis Pramoedya Ananta Toer dan berhadapan dengan penganut sastra humanisme universal yang diusung HB Jassin, Taufik Ismail dkk. Terakhir, perdebatan tentang sastra kontekstual yang disulut Arief Budiman dan Ariel Heryanto di tahun 80-an. Semuanya sama-sama mempersoalkan identitas apakah dipengaruhi ataukah tidak dipengaruhi sesuatu.
- Kategori Nilai (Value)
Dalam menghadapi setiap tindakan tidak hanya dituntut ekspresi, tetapi sekaligus bagaimana evaluasi dan persepsi nilai.
Lingkar Hermeneutik Menurut Gadamer
Tokoh selanjutnya yang memaparkan gagasan tentang hermeneutik adalah Martin Heidegger (1889-1976) dan Hans Georg Gadamer (1900-2002). Jika pada masa Schleiermacher dan Dilthey, hermeneutik menjadi persoalan epistemologis dan lebih menekankan pada intensi pengarang (author), maka Heidegger dan Gadamer justru membawa hermeneutik ke dalam persoalan ontologis. Keduanya juga menilai upaya memahami pengarang adalah hal yang impossible (mustahil) sebab akan selalu ada jarak sejaran (historical distance) antara penafsir dan pengarang. Lingkar Hermeneutik menurut Gadamer:
- Lingkar antara distanciation (jarak sejarah) dengan nearness (kedekatan).
Menurut Gadamer, dalam upaya menafsirkan satu teks, tidak mungkin menghilangkan historical distance atau jarak sejarah antara pengarang dan penginterpretasi. Jarak sejarah tidak pernah bisa dieliminasi karena konteks historis pengarang dan penginterpretasi tidak bisa dipertemukan. Jadi, persoalannya bukanlah bagaimana menghapus jarak tetapi bagaimana membuat jarak menjadi lebih produktif. Bagi Gadamer, sebuah teks masa lampau bisa memberi akses untuk memberikan hermeneutical circle (lingkar hermeneutik) yang tidak pernah putus antara distansiasi (jarak sejarah) dengan kedekatan (effective history).
- Lingkar sejarah sebagai effective history dan sejarah sebagai sesuatu yang tidak dikonstruksi
- Lingkar antara No Ematic Understanding dan No Etic Understanding
No Ematic Understanding adalah what is say. Sedangkan No Etic Understanding adalah act of understanding atau tindakan pemahaman sesuatu. Dialektika keduanya bermakna kita hanya bisa memahami bahasa jika kita mengerti apa yang dikatakan
Dialektika Langue dan Parole
Salah satu tokoh yang juga dianggap mempengaruhi studi hermeneutik adalah ahli linguistik berkebangsaan Swiss yaitu Ferdinand de Saussure (1857-1913). Ia memiliki gagasan tentang adanya struktur bahasa hingga mempengaruhi lahirnya aliran teori dalam linguistik yaitu strukturalisme. Doktrin Saussure adalah bahasa dianggap sebagai obyek dan pada dasarnya memiliki dua aspek yaitu aspek langue dan aspek parole. Linguistik mempelajari aspek langue sebagai aspek sosial dari bahasa. Langue inilah yang memungkinkan berlangsungnya komunikasi simbolik antar manusia karena langue ini dimiliki bersama. Langue dalam konsepsi Saussure mirip dengan Competence dalam pandangan Noam Chomsky. Langue merupakan fenomena kolektif. Dia merupakan sebuah sistem, sebuah fakta sosial (dalam bahas Emile Durkheim) atau aturan-aturan, norma-norma antar personal (interpersonal rules and norms) yang bersifat tidak disadari.
Sedangkan parole adalah bahasa sebagaimana digunakan. Parole adalah apa yang diwujudkan ketika menggunakan sebuah bahasa dalam percakapan atau ketika menyampaikan pesan tertentu lewat suara-suara simbolik yang keluar dari mulut. Menurut Saussure, linguistik struktural sebagai ilmu tidak memperhatikan aspek Parole meskipun dikotomi langue-parole sangat dikenal dalam dunia linguistik.
Saussure juga membedakan antara aspek sinkronis dan diakronis (terkait historisitas) dalam studi bahasa. Namun, ia hanya memberikan prioritas pada bahasa sebagai aspek sinkronis (Ahimsa Putra, 2001). Ia menyadari akan sifat historis dari bahasa serta atau historisitas dari bahasa yaitu bahasa selalu mengalami perubahan. Kenyataan ini menuntut adanya pembedaan yang jelas antara bahasa sebagai sistem dan fakta kebahasaan yang mengalami evolusi..
Ricoeur melihat adanya dialektika di antara langue dan parole. Ia melihat langue memiliki aspek sinkronik, virtual, serta homogen. Sedangkan parole bersifat diakronik, aktual, heterogen, serta pemaknaannya bersifat arbitrer (mana suka). Mengutip Benveniste, parole terdiri dua yaitu rule of government (berbahasa menurut aturan atau gramatika) dan rule of change (berbahasa secara kreatif). Aspek rule of change inilah yang disebut sebagai discourse atau wacana.
Ricoeur dan Dialektika Event-Meaning
Secara harfiah, event berarti peristiwa dan meaning berarti pemaknaan. Event adalah peristiwa ketika bahasa mengalami proses aktualisasi. Unsur-unsur event adalah aktualisasi, mengalir (fleeting), serta temporal. Ketiga unsur inilah yang disebut sebagai discourse (wacana). Menurut Ricoeur, event muncul dari dua hal yaitu bahasa dan discourse. Namun untuk menjadi discourse, harus ada dialektika atau Lingkar Hermeneutik.
Sedangkan meaning dikontrol oleh subyek dan predikat. Menurut Ricoeur, predikat digunakan untuk memberi sifat pada subyek. Antara event dan meaning ini selalu mengalami dialektika. Event mengaktualisasikan meaning tapi tanpa event, meaning tidak akan ada. Dialektika antara event dan meaning ini adalah Lingkar Hermeneutik.
Discourse dapat bersifat lisan, dapat bersifat tertulis. Perbedaan di antara kedua jenis discourse ini tidak hanya terletak pada perbedaan substansi medianya, yang satu substansi auditif, yang lain substansi visual, melainkan terutama sekali pada efek dari perbedaan substansi media itu terhadap kemungkinan bangunan makna dari masing-masing wacana tersebut dan, pada gilirannya, juga terhadap cara pemahaman atasnya.
Ignas Kleden menunjukkan, bahwa berbeda dari fonem, kata, dan sistem bahasa pada umumnya yang bersifat abstrak, kalimat dan discourse adalah peristiwa yang bersifat singular, terikat pada ruang dan waktu. Namun, seperti halnya satuan-satuan bahasa yang terdahulu itu, gejala kebahasaan yang kemudian adalah juga tanda, sesuatu yang bermakna, dan makna itu bersifat universal atau general. Dengan demikian, bangunan makna discourse terdiri dari dialektika antara event (peristiwa) dan meaning (makna).
Makna sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu makna tekstual dan makna referensial. Makna tekstual adalah makna yang terbangun dari hubungan antartanda yang ada di dalam teks, sedangkan makna referensial terbangun dari hubungan antara teks dan dunia luar. Makna referensial itu pun dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu makna referential yang ostensif dan makna referential yang deskriptif. Yang pertama merupakan makna yang dapat dicek dalam dunia empiris yang ada di luar teks, sedangkan yang kedua merupakan makna yang dapat dicek dalam dunia empiris yang direka di dalam teks itu sendiri.
Discourse yang ditulis adalah discourse yang mengalami fiksasi, yaitu telah mengalami pembakuan teks sehingga menjadi benda yang berdiri sendiri, meninggalkan penulisnya. Discourse ini dapat melakukan distansiasi terhadap peristiwa atau konteks penuturannya semula. Karena itu, wacana yang bersangkutan menggantungkan dirinya pada makna yang bersifat universal, yang mampu melampaui ruang dan waktu penuturannya semula, dan memasuki konteks baru dalam pembacaan dari waktu ke waktu atau bahkan mengalami dekontekstualisasi sama sekali.
Namun, kenyataan terakhir di atas tidak dengan sendirinya berarti bahwa wacana itu kehilangan sama sekali hubungannya dengan dunia di luar teks. Hanya saja, hubungan antara teks dan dunia di luar teks itu bukanlah hubungan fungsional, melainkan hubungan simbolik.
 27 Desember 2006
27 Desember 2006