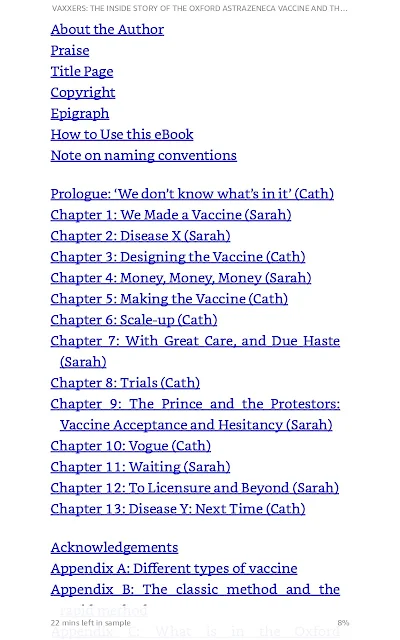|
| saat Erick Thohir berbincang dengan peneliti asal Indonesia di Oxford |
Erick Thohir, Menteri BUMN, memanggil pulang peneliti Indonesia di Universitas Oxford, Inggris, yang punya andil dalam pengembangan AstraZenecca. Namun Erick tidak tahu bahwa di negeri yang tunduk pada investasi asing ini, menjadi buzzer dan tim sukses lebih menjanjikan masa depan ketimbang jadi peneliti.
Di dunia riset, Anda harus meniti karier dari level paling bawah, dimulai dari posisi peneliti junior yang mengerjakan semua hal, termasuk mengambil sampel ke daerah terjauh. Sementara di dunia buzzer dan tim sukses, Anda hanya perlu ikut-ikut tim pemenangan seorang kepala daerah atau calon presiden, setelah itu cukup baca “Bismillah”, langsung dapat posisi Komisaris.
Bayangkan, ada seorang peneliti yang bertahun-tahun kerja di Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan di Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kariernya bermula dari manjat tiang listrik hingga bertahun-tahun kemudian mulai jadi peneliti senior.
Kira-kira, apa responnya saat baca berita tentang Eko Sulistyo, salah seorang tim sukses Jokowi, diangkat sebagai Komisaris PLN. Padahal, belum tentu Eko tahu banyak tentang dunia PLN. Pengetahuan peneliti itu jauh di atas Eko. Bedanya, Eko adalah tim sukses Jokowi. Dia dekat kekuasaan. Ada pula timses Jokowi jadi Komisaris BUMN, yang modalnya hanya memuji Jokowi dan mengolok Prabowo di Twitter.
Bukan hanya di pusat, di level pemerintah daerah juga setali tiga uang. Seorang gubernur bisa saja membentuk TGUPP yang gajinya selangit, jauh di atas peneliti di balitbang milik pemda. Bahkan TGUPP bisa mengendalikan kepala dinas. Siapa yang diangkat jadi TGUPP? Ya tim sukses. Bisa jadi penyusun konsep, jubir di media, angkat-angkat tas, atau barangkali berperan untuk mendatangkan massa saat kampanye.
Di satu daerah di Sulawesi, anggota TGUPP rata-rata bergelar profesor doktor. Para ilmuwan bergelar profesor, yang seharusnya menjadi sumber daya terbaik untuk pendidikan dan riset, tiba-tiba harus mengurusi birokrasi dan anggaran perjalanan dinas di pemda. Ironis.
BACA: Ayo, Dukung Rektor Jadi Komisaris
Lihatlah di sekitar kita. Ada banyak jejak digital di media-media tentang tim sukses yang tadinya hidup pas-pasan, lalu naik kelas begitu calonnya menang. Risetnya Michael Buehler, pengajar di University of London, mengungkap ada banyak tim sukses yang mendapatkan permen berupa proyek begitu kandidatnya menang. Di situ, berlaku hukum take and give. Anda diberi posisi, Anda juga harus menyetor. Ada uang, ada cashback.
Lantas, Erick Thohir mau meminta anak muda yang sedang sekolah di Inggris itu untuk pulang lalu jadi peneliti di tanah air dengan standar hidup pas-pasan, sementara ada kelompok yang hanya kerja sedikit langsung dapat posisi tinggi?
Erick Thohir, yang berlatar pengusaha ini, tidak tahu iklim riset di tanah air kita. Posisi peneliti hanya menempati posisi pinggiran di segala ranah. Di berbagai kantor pemerintah, posisi peneliti di Balitbang, bukanlah posisi yang bagus, sehebat apa pun karya Anda.
Rekomendasi peneliti tidak didengar dalam perumusan kebijakan. Kertas kerjanya hanya berserakan di laci para pejabat. Tulisannya di jurnal hanya dibaca sedikit orang yang tertarik, itu pun hanya kalangan nerd di kampus-kampus yang berteman dengan buku.
Saat badai pandemi Covid-19 datang menyerang, banyak peneliti, ahli-ahli dan epidemolog memberikan jalan keluar. Tapi, rekomendasi mereka kalah nyaring dengan suara seorang pebisnis kakap. Suara peneliti bisa dengan mudah diabaikan saat seorang investor menjelaskan kalkulasi kerugian jika saran peneliti itu dituruti.
Kita tak punya ekosistem riset yang bagus. Idealnya, ada interaksi yang intens antara pengambil kebijakan (dalam hal ini pemerintah), peneliti di perguruan tinggi, serta dunia industri. Ekosistem ini tidak terbentuk, apalagi Kementerian Riset Dikti yang seharusnya jadi perekat ketiganya malah dibubarkan.
Berkat pandemi, kita jadi tahu betapa rapuhnya dunia riset kita. Terlalu jauh jika kita bandingkan dunia riset kita dengan Inggris dan Amerika Serikat. Di Asean saja, kita tertinggal jauh.
Rasio jumlah peneliti dengan jumlah penduduk di Singapura adalah lebih dari tujuh ribu peneliti per satu juta penduduk. Sedangkan di Malaysia sebanyak 2.590 peneliti per satu juta penduduk. Sementara di Indonesia, rasionya hanya sebesar 1.071 peneliti per satu juta penduduk. Angka rasio ini pun sudah termasuk dosen di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
Jika sains adalah senjata, dan peneliti adalah pasukannya, maka jelas kita tak berdaya dalam menghadapi situasi darurat yang membutuhkan kerja-kerja peneliti. Kita tak mungkin setangguh Inggris.
Dalam buku Vaxxers: The Inside Story of The Oxford Vaccine and The Race Aigainst Virus, Profesor Sarah Gilbert bercerita tentang proses riset menahun yang telah dibuat Jenner Institut, Oxford University, sebelum membuat vaksin Oxford AstraZeneca. Dia mengibaratkan prosesnya seperti membuat kue, di mana adonannya sudah lama ada dan siap, sehingga proses berikutnya tinggal meletakkan pewarna di atas kue.
Sejak lama, mereka meneliti berbagai varian virus, mulai Ebola, sampai Mers. Mereka sudah lama membuat template, sehingga ketika ada satu virus menyerang, mereka tahu bagaimana menyiapkan vaksinnya. Vaksin AstraZeneca kelar dalam waktu 12 bulan, sementara peneliti kita entah kapan bisa keluar.
Tapi riset di Oxford itu butuh bertahun-tahun dan selalu dibiayai negara. Pemerintah menyediakan anggaran untuk proses riset yang panjang di perguruan tinggi, yakni Universitas Oxford, kemudian ada dukungan kuat dari dunia industri yakni AstraZeneca. Hebatnya, para peneliti ini menolak mamatenkan vaksinnya agar bisa terjangkau warga dunia.
BACA: Peneliti yang Jadi Berkah bagi Semesta
Namun cerita-cerita hebat begini akan sulit kita temukan di tanah air kita. Rasanya sulit kita mendapati tim peneliti yang bekerja bertahun-tahun kembangkan riset dengan dukungan dana yang kuat dari negara.
Kerja peneliti tidak dihargai, apalagi jika penelitian itu tidak ada kaitannya dengan mendatangkan investasi, serta industri 4.0. Anggaran riset kita amat minimalis. Pemerintah kita ingin sesuatu yang jangka pendek, dan mudah terlihat. Pemerintah tidak tertarik dengan program jangka panjang, yang hasilnya belum tentu terlihat dalam satu periode. Di sisi lain, peneliti hidup dengan gaji pas-pasan.
Tengoklah pengalaman Burhanuddin Muhtadi yang dibagikannya di Twitter. Lulus dari program doktor di Australian National University (ANU), dia kembali kerja di kampus sebagai akademisi dan peneliti. Gajinya hanya sekitar tiga juta rupiah.
Gajinya lebih rendah dari besaran gaji UMR untuk buruh di Jakarta. Gaji segitu sama dengan seorang buruh pabrik sepatu di Bogor, yang pendidikannya hanya sekolah dasar. Dia banting stir kerja di lembaga survei, konsultan, pengamat politik, hingga menjadi narasumber.
Makanya, mending anak muda di Oxford, yang dipanggil Erick Thohir itu, tidak pulang. Lebih baik dia bekerja di Inggris yang punya keberpihakan pada riset. Lebih baik bekerja di ekosistem di mana fasilitas laboratorium sangat lengkap sehingga potensinya bisa terus berkembang dan membuat banyak hal yang menyelamatkan dunia.
Namun jika dia memaksakan untuk pulang tak apa. Selain jadi peneliti, dia bisa nyambi sebagai buzzer, biar kelak dia bisa masuk ring satu kebijakan, dan mendorong agar ada perhatian pada dunia riset. Riset jalan, tapi cuan juga datang. Siapa tahu bisa jadi “Bismillah Komisaris.”