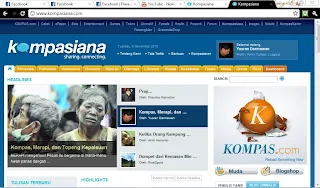PADA awalnya adalah suara senyap. Namun ketika sosok itu mulai berbicara, sorak-sorai membahana serentak memenuhi ruangan. Tepat di auditorium Universitas Indonesia (UI), pria itu berbicara dengan kalimat yang amat bersahabat, menarik, serta penuh keakraban. Pria berkulit gelap itu adalah seorang presiden. Namun ia tidak sedang berbicara di hadapan bangsanya sendiri. Ia berbicara di hadapan bangsa lain, pada negeri yang didiaminya selama beberapa tahun. Namun simpati yang didapatkannya luar biasa dahsyat.
 |
| saat Obama berpidato di kampus UI |
Saya sedang membahas seorang pria bernama Barrack Husein Obama, pemimpin sebuah negara adidaya dan superpower Amerika Serikat (AS). Ia datang di satu negeri yang warganya demikian lama menantikan kedatangannya. Saya berani bertaruh. Saat dirinya berpidato, pasti ada begitu banyak pasang mata yang menantikannya melalui layar televisi dengan berdebar-debar. Obama menjawab semua harapan public dengan antuasiasme serupa. Ia menyebut hal-hal yang menggembirakan dan menjadi benang merah yang mempertautkan dirinya dengan bangsa Indonesia.
Kemarin, saat dirinya berpidato di kampus UI, kembali semua berdecak kagum. Dengan gaya retorik yang piawai dan khas, ia mendulang simpati publik. Seorang kawan mahasiswa tak kuasa menahan rasa bahagia yang teramat sangat. Ia mengirim SMS kepada saya dengan ucapan singkat, “Andaikan dia memilih naturalisasi dan mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia, maka saya akan menjadi orang pertama yang akan memilihnya. Saya akan menciptakan sejarah bersamanya.”
Sehebat itukah respon kepadanya? Pantaskah kita memberikan respon demikian besar pada presiden dari negeri yang jauh? Saya termenung kala mengamati pesan teman tersebut, serta menyaksikan komentar yang berseliweran di fesbuk. Mengamati begitu banyak komentar tentang Obama, saya sering merasa terheran-heran. Saya sedang menyaksikan sebuah gelombang kekaguman yang mengalir rapi sejak berita kedatangan Obama di negeri ini. Ia memang banyak dikritik, khususnya oleh kelompok tertentu, namun fakta juga mengatakan bahwa ia dinanti bak seorang selebritis kesohor. Media televisi ramai-ramai menurunkan liputan eksklusif, yang paling meriah jika dibandingkan Presiden AS manapun yang pernah berkunjung ke negeri ini.
Memang, kita dengan mudah bisa mengatakan bahwa semua antusiasme itu dipicu oleh fakta tentang sosok Obama yang pernah tinggal di Jakarta selama beberapa tahun. Ia mengenal dan mengingat negeri ini dengan baik, dan beberapa kali mencatatnya dalam buku, atau disampaikan dalam pidato yang menggemuruh di negeri Paman Sam. Namun, saya justru melihat sesuatu yang lebih luas.
Bagi saya, simpati dahsyat itu tidak semata-mata karena factor hubungan kultural yang kuat. Saya melihat bahwa simpati itu lahir dari pidato yang mempesona, pribadi yang charming dan bersahabat, serta visi yang mengalir deras dan membangkitkan optimisme. Selain itu, bangsa ini memang merindukan satu sosok yang memiliki pidato yang menyentuh, memiliki kecerdasan dan sikap yang tegas dan mengalir lewat pancaran kata-kata. Kelebihan Obama, sebagaimana yang saya saksikan di televisi, adalah gaya retorika yang menyihir, kemampuan menyerap idiom-idiom lokal, kemudian membahasakannya pada audiens lokal. Kombinasi dari semua ini memunculkan sebuah pidato yang amat menyentuh hati dan memekarkan semangat. Inilah kekuatannya.
Retorika Dua Presiden
 |
| jamuan dua presiden |
Mengapa public demikian gemuruh? Sebab selama ini public dipertontonkan gaya pidato yang agak monoton dan cenderung textbook. Pada saat Obama didampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sama-sama berbicara, saya melihat ada kesamaan di antara mereka yakni sama-sama terpilih dari pemilu yang pesertanya adalah jutaan orang. Nah, jika membandingkan keduanya, tentu akan sangat menarik sebab kedua-duanya sangat menjaga citra sebagai unsure utama yang menggiring ke pucuk pimpinan. Namun, bagaimanakah kiat mereka membangun retorika? Apa yang bisa dicatat dari perbedan gaya retorik mereka? Nah, pembahasan ini hanya focus pada gaya retorika saja. Tidak melebar ke hal-hal lainnya.
Pertama, Obama amat fleksibel dalam hal bahasa tubuh (body language). Ia melemparkan senyum sana-sini, dan menjawab pertanyaan berdasarkan spontanitas. Sepintas, ia seolah tidak sedang serius dalam menghadiri sebuah acara kenegaraan. Ia seperti sedang bermain-main dan berprilaku seperti seorang sahabat yang santai, namun tetap serius. Sesekali ia melontarkan kalimat yang melahirkan gerr atau tawa. Dengan bahasa tubuh yang demikian akrab dengan siapa saja, ia mencitrakan dirinya bukan sebagai orang lain. Sangat jarang ia memasang satu sikap sempurna yang kaku, jarang menoleh kiri kanan, serta wajah yang ditekuk seolah-olah sedang menghadapi arena pertempuran. Senyumnya mengembang. Sejak pertama turun dari pesawat, ia tersenyum lebar dan menyapa semua orang. Ia tidak sekadar berjabat tangan dengan senyum kaku dan dipaksakan. Ia singgah sejenak lalu mengajak siapapun untuk berbincang.
Saya melihat bahasa tubuh ini amat berbeda dengan Presiden SBY. Mungkin karena besar dari latar militer, membuat SBY amat menaati keprotokoleran. Sepintas, sikapnya agak kaku. Senyumnya agak datar. Saya jarang menyaksikan SBY tertawa lebar sebagaimana Gus Dur ketika sedang berguyon atau ketika sedang diledek oleh pelawak Srimulat. Ketika berjalan, SBY agak kaku dengan langkah yang amat tegap, seperti prajurit yang sedang menuju medan laga. Ia memang lebih banyak diam, dan memancarkan kharisma. Namun, dengan style seperti itu, ia jadi misterius dan seperti membangun benteng kehati-hatian. Berbeda dengan Obama yang fleksibel.
Kedua, pilihan kata. Bagi saya, Obama adalah seorang maestro yang pandai memilih kata. Media massa amat senang mengutip kalimat Obama karena pilihan katanya yang tepat serta menyentuh. Kalimatnya tidak sekadar berisi, namun juga penuh daya pesona yang membelit semua pendengarnya. Saya mencatat kutipan pidatonya saat terpilih sebagai Presiden AS. Ia mengatakan, “If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. This is America!”
Kemarin, saat ia memulai pidato di UI, ia tidak memulai dengan kalimat “Yang terhormat……” sebagaimana sering dipakai para pejabat kita. Ia justru memulai dengan menatap ke segala arah, kemudian tersenyum dan sedikit mendehem, lalu berkata, “Pulang kampung nih..”. Anda tahu sendiri bahwa reaksi public adalah gemuruh bertepuk tangan. Sims Wyeth, seorang pelatih dan konsultan komunikasi oral, mencermati dimana kekuatan pidato Obama. Ia mengatakan kekuatan Obama adalah concern audience. Ia selalu membuka pidato dengan cerita-cerita yang menarik dan membuat siapapun tersenyum. Saat inilah ia akan mengeluarkan kalimat yang berisi.
Nah, saya justru tidak menemukan itu pada pidato SBY. Sejak masa Presiden Soeharto, kita selalu menyaksikan retorika yang agak menjemukan. Boleh jadi, para pemimpin kita hanya mengandalkan para intelektual bergelar professor untuk menyusun pidato. Makanya, retorika yang muncul adalah retorika ilmiah dan tidak membawa kekuatan apapun. Gaya pidato Presiden SBY adalah sering membaca naskah yang disodorkan dengan intonasi yang datar, tanpa ekspresi.
 |
| gerakan tangan yg khas |
Dari sisi content, saya jarang menemukan kalimat-kalimat yang berisi dan terngiang-ngiang dalam benak. Sering saya berpikir, mengapa pemimpin kita hanya mempekerjakan para ahli hukum seperti Yusril Ihza Mahendra (penyusun pidato Suharto) untuk menyusun pidato? Demikian pula SBY yang sempat mempercayakan naskah pidato pada Dino Patti Jalal yang latarnya ahli politik. Mengapa SBY tidak berkonsultasi dengan penyair seperti Goenawan Mohammad untuk menyusun kalimat yang berisi dan menyentuh hati? Bukankah pidato yang kering itu akan basah dan mengalir lembut jika diberi sentuhan humaniora?
Ketiga, sentuhan emosi. Obama pandai membaca apa yang sedang ditunggu-tunggu para audiensnya. Dengan cara mengutip beberapa kalimat tertentu, ia menjadikan dirinya sebagai bagian dari audiensnya. Ia mengatakan, “Indonesia bagian dari diri saya.” Ia lalu menceritakan dalam bahasa Inggris, ibunya menikahi pria Indonesia, Lolo Soetoro. Kemudian Jakarta yang dikenalnya. Ia masih ingat Hotel Indonesia dan juga pusat belanja Sarinah. “Ada bemo, banyak mobil juga sekarang.” Obama juga bercerita dulu dia tinggal di Menteng Dalam. Ucapan ini disambut teriakan-teriakan mahasiswa. Obama pun tertawa sambil berucap, “Hei, ada yang dari Menteng Dalam juga ya,” cetusnya sambil tertawa.
Sehari sebelumnya, ia memuji masakan Indonesia. Feeling saya, mungkin Obama tidak menghapal lagi hingga detail. Tapi, saya yakin Obama memiliki sejumlah tim yang datang lebih dulu, mengumpulkan banyak informasi tentang Indonesia, dan memberikan masukan apa yang harus diucapkannya. Makanya, jangan pula terkejut ketika Obama membahas Pancasila dan dikaitkan dengan semangat pluralism, Unity in Diversity. Semuanya berkat masukan dan kerjasama apik dengan tim kerjanya. Dengan mengambil idiom cultural seperti ini, ia akan diterima bak warga setempat yang pulang merantau. Luar biasa!
Lagi-lagi saya tidak menemukan pendekatan cultural dalam pidato SBY. Dengan pidato yang datar serta bahasa yang baik dan benar itu, SBY terkesan kaku dan agak serius. Presiden SBY yang jarang mengadopsi pendekatan cultural dalam naskah pidatonya. Ia jarang mengutip pendapat sosok besar negeri ini di masa silam. Sangat berbeda dengan pidato Bung Karno yang melahirkan banyak kalimat popular yang membekas, misalnya “jangan sekali-kali merubah sejarah” (jasmerah), atau kalimat “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya.” Atau mungkin anda masih ingat kalimat “Go to hell with your aid.” Memang, di antara semua pemimpin kita, hanya Bung Karno yang bisa mengalahkan kepiawaian Obama ketika berpidato.
Tapi bukan berarti pidato SBY tidak menarik. Justru pidatonya akan sangat menarik jika di banyak negara, Presiden SBY juga mengadopsi pendekatan kultural, mengidentifikasi apa strategi kultural yang tepat di negara tersebut, kemudian menerapkannya dalam pidato. Saya yakin pidatonya akan lebih bermakna. Sebagai seorang yang berasal dari daerah, dalam hal ini Pulau Buton, saya membayangkan suatu hari Presiden SBY akan berkunjung, kemudian menyampaikan salam dalam bahasa Buton. Bukankah Buton adalah bagian dari wilayah kekuasaannya yang semestinya dikenali nilai kearifan lokalnya? Saya membayangkan, ia akan berpidato dan sesekali mengutip falsafah Buton. Apakah susah melakukannya? Tidak. Ia tinggal menurunkan tim, kemudian mempelajari idiom kultural, lalu mengemasnya menjadi pidato yang menarik dan menyentuh hati warga setempat.
***
Masih banyak yang hendak saya sampaikan di sini. Mulai dari substansi pembicaraan, wawasan, isu penting pembicaraan, gerak tangan, hingga bagaimana mengelola perhatian audiens. Sayang sekali karena tidak dibahas dalam tulisan ini, sebab bisa kepanjangan dan melelahkan anda semua para pembaca.
Catatan penting yang bisa diketengahkan di sini adalah kebanyakan pemimpin negara kita justru bukan mereka yang cakap dan pandai berpidato dengan bahasa yang menyentuh. Saya sudah terbiasa menyaksikan gaya retorik para pemimpin kita yang datar, tanpa ekspresi, dan terkesan membaca teks. Banyak pemimpin kita yang tidak berwawasan luas. Tidak semua mengenali khasanah kekayaan bahasa serta petuah bijak yang terangkum dalam sejarah.
Ketika Obama dielu-elukan, maka itu adalah cerminan dari kerinduan pada sosok yang kalimatnya menyentuh, tertata rapi serta menunjukkan wawasan yang luas dan pemahaman yang baik atas sebuah permasalahan. Kita menginginkan ada sosok yang tegas, dan membangkitkan harga diri bangsa dalam pergaulan internasional. Lebih dari itu, kita merindukan sosok sejuk yang kalimatnya mempesona, menjerat semua hati dan simpati, serta membangkitkan optimism. Bukankah itu hal-hal yang kita harapkan dari seorang pemimpin?
Jakarta, 11 November 2010
Saat terbangun subuh-subuh