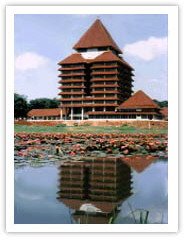APA arti seorang cendekiawan? Apa arti
APA arti seorang cendekiawan? Apa arti menjadi intelektual? Intelektual adalah sosok yang mengobarkan api ilmu dan membakar belukar ketidaktahuan manusia. Mereka adalah sosok yang membawa pencerahan demi membawa terang peradaban.
Sosok ini bukanlah mereka yang duduk tenang di bangku akademis sembari memamah biak seluruh bangunan teori asing dan mengutipnya secara asal. Ia bukanlah mereka yang terjebak dalam kegenitan intelektual sembari menatap sinis pada tradisi negeri yang berdenyut dalam darahnya.
Intelektual adalah kupu-kupu harapan bagi sebuah negeri yang tengah beringsut menuju kemajuan. Sosok yang menjadi pembebas dan tercatat dengan gemilang dalam berbagai kitab suci dan kitab peradaban manusia.
Jika seseorang hanya bisa mengucapkan nyanyi sunyi ketika ketidakadilan dan ketimpangan bersemayam di depan mata, maka tentu dia bukan intelektual. Sebab intelektual memiliki apa yang disebut filsuf Heidegger sebagai sesuatu yang bisa membawa terang dan memisahkan gelap dalam hidup.
Luka bagi masyarakat adalah luka bagi kaum intelektual. Pedih bagi masyarakat adalah pedih bagi kaum intelektual. Di saat bersamaan lahir ikhtiar untuk merefleksikan seluruh gejolak masyarakat dengan penuh kejernihan dan tanpa takut.
Jumlahnya tentulah tidak banyak. Sebab kehadiran mereka semata-mata adalah membawa pesan suci untuk membangkitkan kerajaan Ilahi di muka bumi.
Bagi saya, intelektual tidak sekedar kategori capaian intelektual. Ia juga merangkum kategori eosional serta spiritual. Faktor yang paling penting adalah ia harus punya andil dalam mereleksikan zaman serta membangun upaya sistematis untuk melakukan rekayasa sosial untuk zaman yang lebih baik.
Saya selalu berkeyakinan kalau jumlah intelektual itu tidak banyak. Sejarah mencatat kalau mereka tidak banyak sebab hanya menjadi noktah kecil dalam perjalanan sejarah.
Barangkali asumsi ini terlampau berlebihan. Mungkin. Namun, jika melihat pemetaan intelektual Indonesia kontemporer, akan terang benar kalau mereka adalah mahluk yang langka di republik ini.
Di negeri ini, kategori intelektual hanyalah menjadi label dari mereka yang mendedikasikan ilmunya sebagai alat kekuasaan. Sekadar menjadi sekrup kecil dari mesin raksasa bernama pembangunan. Sekadar meneguhkan kekuasaan dan mempreteli hak-hak rakyat.
Jangan heran jika menemukan fakta akan banyaknya mereka yang mengatasnamakan intelektual. Mereka menempati banyak posisi penting baik di pemerintahan maupun parlemen.
Mereka menjadi pengabsah dan tim ahli di balik lahirnya sebuah kebijakan. Mereka menjadi komunitas epistemik yang meramaikan debat dan wacana di dalam jantung sistem bernama negara.
Komunitas epistemik ini beranggotakan sejumlah orang yang mengaku intelektual dan menjalankan berbagai kegiatan demi meneguhkan rezim yang dibelanya. Tugas mereka adalah merefleksikan berbagai kebijakan yang hanya mendukung pemerintah.
Studi dari Daniel Dhakidae berhasil memetakan sejumlah intelektual di zaman Orde Baru yang memiliki peran dalam negara. Di seberang temberang dari intelektual pro negara, ada pula sejumlah intelektual yang memposisikan dirinya untuk membangun wacana tanding (counter discourse) pada berbagai kebijakan negara.
Demikian pula dengan studi Yudi Latif tentang intelektual Indonesia pasca-Orde Baru. Kita diosodori dengan fakta betapa jumlah mereka hanya seperti bilangan jari di tengah warga Indonesia yang mencapai 240 juta orang.
NANTI SAYA LANJUTKAN