HARI itu, suhu tubuh anak saya Mahavidya
Sarasaty (Ara) meninggi. Semalam suntuk ia tak bisa tidur dan hanya bisa
menangis. Tadinya saya pikir sakitnya akan segera berlalu. Ternyata panasnya
malah meninggi. Saya lalu membeli termometer di toko CVS lalu mengukur suhu
tubuhnya. Termometer itu lalu menunjuk angka 103 Fahrenheit. Istri saya
mendesak untuk segera membawa Ara ke rumah sakit. Ia harus diperiksa dokter.
Jika ia sakit di tanah air, saya tak ragu
membawanya. Saya paham seberapa banyak biaya yang harus saya siapkan. Namun
saat itu kami di Ohio, Amerika Serikat (AS). Saya perkirakan pasti biaya rumah
sakit sangatlah mahal. Saya juga tak paham bagaimana kultur para dokter ketika
memeriksa pasien. Namun saya tak punya pilihan. Saya tak tega melihat Ara sakit
demam dan terus-terusan menangis. Sebagai ayah, hati saya teriris-iris.
Kami lalu ke rumah sakit O’blenes. Ketika tiba,
Ara dibawa ke sebuah bangsal untuk menunggu dokter. Perawat lalu memanggil
saya. Ia bertanya dan mencatat tentang nama dan alamat apartemen tempat saya
berdomisili. Saya pikir perawat itu akan menyebut biaya perawatan atau minimal
biaya pemeriksaan. Ternyata sama sekali tidak. Perawat lalu mempersilakan saya
untuk kembali ke tempat Ara dan ibunya menunggu di satu bangsal. Perawat itu lalu
bertanya beberapa hal, kemudian berkata bahwa dokternya akan segera datang.
Belakangan saya baru tahu kalau rumah
sakit di Ohio tidak pernah membicarakan biaya pada saat pasien datang. Semua
pasien akan langsung dirawat dengan fasilitas terbaik yang dimiliki rumah sakit
hingga pasien itu sembuh. Tiga bulan setelah sehat, barulah rumah sakit akan
mengirimkan rincian tagihan biaya pengobatan. Pihak rumah sakit berprinsip
bahwa biaya adalah urusan belakangan. Ketika pasien datang, maka ia wajib
dilayani. Makanya, ada joke atau lelucon di Ohio bahwa rumah sakit adalah
tempat untuk mencari kesembuhan, namun setelah tiga bulan, ia akan mengirim
penyakit stres ke rumah kita.
Tak sampai setengah jam, dokternya datang.
Ia menjabat tangan saya lalu menyebut namanya Maria Strus. Ia juga datang
menyentuh dahi anak saya, kemudian bertanya beberapa hal kepada istri saya. Maria
lalu memperhatikan dengan teliti setiap keterangan, lalu mencatatnya pada buku
yang dibawanya. Ia mengeluarkan termometer yang lalu dipasang di jari anak
saya. Kemudian, ia meminta agar anak saya dibaringkan di ranjang yang tersedia.
Ketika memeriksa telinganya, dokter Maria itu
langsung menemukan sumber masalahnya. Ara mengalami gangguan infeksi di
telinganya. Ia harus meminum antibiotik pada dosis tertentu. Dokter itu
menjelaskan tentang sebab-sebab penyakit, setelah itu ia memberikan resep obat.
Saya lega karena Ara tidak harus menginap di rumah sakit. Kami diminta menunggu
selama beberapa menit. Tak lama kemudian perawat datang sambil membawa resep
dan beberapa lembar kertas kuning. Saya diminta untuk membaca dengan teliti
kertas-kertas itu.
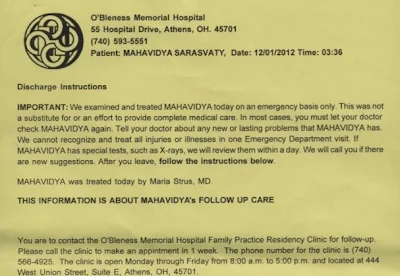 |
| informasi tentang penyakit |
 |
| informasi tentang diagnosis |
 |
| instruksi untuk di rumah |
Pada lembar awal kertas itu, terdapat nama
lengkap Ara, serta nama orangtuanya. Lalu, ada informasi tentang penyakit yang
dialami Ara. Penjelasannya ditulis dalam bahasa yang sopan dan mudah
dimengerti. Ia menjelaskan dengan detail tentang virus, bagaimana menghadapi
virus, apa yang harus dilakukan di rumah, serta beberapa pesan bijak bahwa dukungan
keluarga adalah kekuatan utama dalam proses penyembuhan. Terakhir, ia merinci
obat-obat apa saja yang akan dimakan oleh anak itu. Penjelasannya sangat
detail, dan mudah dipahami.
Sebagai bapak, saya langsung paham apa
yang menimpa anak saya. Penjelasan dokter itu juga menjadi patokan bagi saya
untuk menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan. Saya akhirnya tahu bahwa
sakit anak saya adalah sesuatu yang umum terjadi, khususnya jelang musim
dingin. Yang paling saya senangi adalah penjelasan serta upaya mengedukasi
masyarakat luas tentang penyakit yang diderita, serta bagaimana para dokter itu
membumikan konsep-konsep kedokteran yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana
dan mudah dipahami.
Sebuah Refleksi
PEPATAH lain ladang lain belalang dan lain
lubuk lain ikannya juga berlaku di sini. Di berbagai penjuru tanah air, para
dokter sedang meradang. Demi rekan-rekan sejawatnya, mereka lalu menggelar
demonstrasi di banyak kota. Mereka mogok saat memberikan pelayanan, lalu
membiarkan banyak pasien terlantar di rumah-rumah sakit. Mungkin saja mereka
hendak berkata bahwa perubahan selalu membutuhkan korban. Tak masalah jika
beberapa jam tak ada pelayanan. Yang penting hak bersuara telah ditunaikan.
Terus terang, saya tak seberapa paham
duduk perkara sehingga para dokter itu berdemonstrasi. Saya hanya mendengar
bahwa di Manado sana, tempat yang menjadi awal dari api yang menyebar ke
mana-mana, ada seorang pasien meninggal dunia. Keluarganya lalu menggugat sang
dokter. Di tingkat pengadilan tinggi, dokter tak bersalah. Namun Mahkamah Agung
(MA) memvonis dokter itu bersalah sehingga dokter itu dipenjarakan. Maka
proteslah para dokter di seluruh Indonesia.
Saya hanya bisa mereka-reka. Di media,
banyak orang mengeluarkan bahasa hukum dan bahasa teknis untuk memahami masalah
ini. Tapi saya ingin melihatnya dari sisi lain. Saya melihat satu elemen yang
hilang yakni tak adanya proses komunikasi yang equal dan harmonis. Dokter bekerja dengan dunia sains yang teknis
dan mekanis. Ia tak hendak membumikan istilah itu sehingga dipahami pasien
ataupun keluarga pasien. Keduanya tak saling memahami. Sang dokter tak
berempati ada keluarga korban. Ia hanya memeriksa, lalu mengoperasi. Dan ketika
korban menghembuskan napas terakhir, tak ada pula penjelasan tentang apa yang
sedang terjadi.
Sementara masyarakat luas, termasuk
keluarga korban dan jaksa, melihat ada sesuatu yang keliru di sini. Mereka
memang tak paham istilah-istilah medis. Akan tetapi, ada rasa haus akan kebenaran
yang tak penah terpuaskan. Ketika dokter sibuk dengan dunianya dan tak membuka
ruang-ruang untuk berkomunikasi, maka masyarakat akan melihatnya dengan cara
berbeda. Konflik bisa muncul di situ.
Kemarin, seusai demonstrasi, media sosial
dipenuhi kritik pada para dokter. Saya semakin yakin bahwa banyak hal yang
susah dipahami masyarakat awam atas apa yang mereka lakukan. Susahnya karena relasi
dokter dan pasien tak seimbang. Dokter punya otoritas yang lebih tinggi. Ia
dianggap tahu segala hal tentang pasien yang ditanganinya. Masyarakat menjadi
pihak yang tak banyak tahu. Ketika konsultasi, dengan mudahnya dokter menyebut
biaya pegobatan, tanpa ada ruang bagi masyarakat untuk tahu mengapa biaya tertentu
cukup mahal.
Masyarakat juga ‘dipaksa’ paham bahwa
peristiwa meninggalnya pasien adalah sesuatu yang dianggap wajar di ranah medis
karena sebab-sebab yang sukar diprediksi. Andaikan yang meninggal itu adalah
keluarga dokter, apakah kematian itu menjadi hal yang sederhana?
Idealnya, pasien dan keluarganya adalah mitra yang diajak berdiskusi. Di tanah
air kita, tak semua dokter bersedia untuk mengedukasi pasien dan keluarganya. Malah
banyak di antara dokter yang menghadapi pasien sebagaimana motor rusak yang
harus dibenahi. Pasien langsung ditangani. Tak ada dialog. Tak ada interaksi
dengan keluarga korban. Bahkan ketika korban telah meninggal, tak ada pula
permaafan serta penjelasan kepada keluarganya. Laiknya motor rusak yang tak
bisa diperbaiki, korban dikembalikan begitu saja di rumah. Di titik ini kita
tak lagi berbicara tentang nilai-nilai kemanusiaan.
 |
| tampak luar |
 |
| ruang unit gawat darurat |
Jika saja dokter di Manado itu menjelaskan
dengan persuasif serta menginformasikan banyak aspek pengobatan, maka kasus ini
tidak akan merebak luas. Jika saja para dokter bekerja dengan penuh empati dan
memahami apa yang dirasakan keluarga korban, tentunya kasus ini bisa dihindari.
Setidak-tidaknya, ketika ruang komunikasi terbuka, maka semua pihak bisa
memahami posisi masing-masing. Dokter paham akan keingintahuan keluarga atas
kondisi keluarganya, dan keluarga pasien juga paham tentang tindakan medis yang
harus dilakukan para dokter.
Belajar dari pelayanan dokter di Amerika,
seyogyanya, dokter di tanah air harus belajar banyak aspek persuasif serta
komunikasi dengan pasien. Mereka mesti melihat pasien sebagai subyek yang harus
didengarkan dan dipahami. Memosisikan pasien sebagai motor rusak, yang
dioperasi lalu setelah itu lepas tangan, adalah sesuatu yang keliru. Kurikulum
di sekolah tinggi kedokteran mesti mencakup aspek sosiologis, antropologis, dan
komunikasi. Dengan cara demikian, dokter tak hanya memahami hal teknis, namun
juga bisa menyentuh pasien dari hati ke hati, memosisikan mereka sebagai
keluarga yang butuh kasih sayang dan perhatian, serta bekerja dalam iklim
saling memahami dengan pasiennya. Semoga demikian adanya di masa depan.


0 komentar:
Posting Komentar