ADA lagi bom meledak. Di Samarinda, saya
mendengar kisah tentang empat anak yang menjadi korban pelemparan bom molotov.
Kejadiannya di Gereja Oikumene, Minggu (13/11). Anak-anak itu menderita luka
bakar di sekujur tubuhnya. Anak-anak itu kelak akan dewasa sembari membawa
bekas luka, semacam jejak yang mengingatkan mereka pada satu peristiwa
traumatik di masa silam.
Bagi kita, peristiwa itu hanya menjadi
sebaris kejadian yang keesokan harinya akan segera berlalu. Tapi bagi anak-anak
itu, peristiwa itu akan menjadi trauma, ingatan yang saat dikenang bisa
menghadirkan sembilu yang mengiris hati. Mungkin, anak-anak itu akan membawa
rasa perih setiap kali melihat bekas luka bakar itu. Mungkin, selama
bertahun-tahun, mereka akan bermimpi buruk tentang seorang lelaki yang datang
dengan memakai kaos bertuliskan jihad, lalu melempar bom. Duarr!!! Dunia lalu
mengabur.
Saya berharap anak-anak itu tidak punya
selapis benci pada keyakinan yang menuntun lelaki pelempar bom itu. Lelaki itu
ibarat sosok Silas dalam novel Da Vinci Code karya Dan Brown,
yang menjalankan perintah untuk menebar teror. Silas melaksanakan pesan itu
dengan kesadaran penuh kalau dirinya sedang menjalankan perintah Tuhan,
meskipun itu adalah teror.
Lelaki pelempar bom itu merasa sedang
sedang menegakkan kebenaran. Ia merasa sedang memurnikan ajaran Tuhan yang
mengirimkan rasul sebagai berkah bagi alam semesta. Di situ ada harapan yang
dikuatkan dengan bara keyakinan untuk menegakkan kebenaran. Dan bara itu
selanjutnya serupa magma yang panas dan memuntahkan amarah. Maka mengamuklah
dirinya, lalu menyebut-nyebut nama Tuhan, lalu dengan heroik melempar bom.
Saya terkenang John Lennon yang
bersenandung, “Imagine, there’s no heaven. Imagine there’s no country,
there’s no religion too.” Jika saja tak ada kehidupan serba indah langit,
barangkali manusia tak akan menjalankan misi-misi untuk menggapai kehidupan
yang lebih sempurna. Namun, semuanya kembali pada seperti apa kita memandang
langit. Jika kita melihatnya penuh amarah, maka kita dalam keadaan serba takut
jika melanggar perintah. Jika kita melihatnya serupa ibu yang penuh kasih
sayang, kedamaian akan selalu hadir dalam diri.
Di tanah air Indonesia, agama
belum dimanifestasikan untuk merawat kehidupan yang lebih baik. Belum
menjadi pedoman atau kompas ke mana kehidupan ini bergerak. Agama
dijelmakan sebagai sebuah kategori sosial. Semacam penanda atau identitas
sebuah kelompok. Mungkin saja, dia yang melempar bom itu hendak berkata, aku
benar dan kamu bukan. Ketika kamu kafir dan sesat, kamu tidak berhak atas cinta
kasihku. Kamu tak berhak atas keadilanku. Kamu tak berhak menerima rahmat atas
seru sekalian alam, serta kedamaian yang terpancar dari hati.
Mungkin lelaki pelempar bom hendak berkata
kamu layak menerima amarahku. Mungkin dia hendak berteriak ketika kamu berbeda,
maka kamu telah mengancam diriku. Maka sesatlah kamu dan bakal menerima nasib
para umat yang pernah diperangi dan ditimpakan azab. Mungkin saja lelaki itu
membaca kitab dan menemukan catatan tentang para umat yang ditenggelamkan ke
dasar bumi, diberi azab berupa banjir besar atau api yang turun dari
langit. Dia ingin mengambil peran Tuhan, menebar azab ke mereka yang
berbeda.
***
SAYA sedih membayangkan wajah kanak-kanak
tak berdosa itu. Rasa-rasanya air mata ini tumpah untuk kesedihan yang dengan
segera menggantikan bahagia mereka saat bermain. Di hari Minggu, kanak-kanak
datang ke rumah ibadah bersama orangtuanya. Saat orangtuanya beribadah, mereka
akan bermain dengan riang. Tawa ria dan senyum mereka adalah unsur penting yang
menandakan kehadiran Tuhan. Di rumah ibadah itu, mereka bermain dengan penuh
bahagia. Hingga akhirnya peristiwa itu terjadi.
Sebuah bom berisikan pesan yang hendak
digemakan ke mana-mana. Pesan itu lahir dari kristalisasi pengalaman dan
pembelajaran yang diterima di banyak ranah kehidupan. Si pembom itu merasa
sedang menegakkan nilai dan ajaran. Ia menyasar mereka yang berbeda sebab
dianggapnya kafir dan sesat. Si pembom tak sempat melakukan refleksi dan
kontemplas mendalam, kalau-kalau justru dirinya yang jauh dari titian nilai
kebenaran.
Bagi anak-anak itu, keyakinan keberagamaan
hanyalah satu konsep yang sukar dipahami pikiran kecil mereka. Mereka tak paham
bahwa dunia yang dijalaninya adalah dunia yang serba terkotak-kotak.
Orang-orang saling membangun tembok-tembok yang fundasinya dikukuhkan oleh iman
dan keyakinan. Saat iman tak sama, dialog dan kesepahaman tak selalu terjadi.
Perbedaan itu merambah ke dimensi politik, ekonomi, dan budaya.
Anak-anak itu tidak tahu menahu tentang
bahwa perbedaan keyakinan kerap kali menjadi tembok pemisah. Anak-anak itu
tidak tahu bahwa jika kelak mereka dewasa lalu ingin menjadi pemimpin di satu
wilayah, keberagamaan dan keyakinan mereka akan dipertanyakan banyak orang,
yang justru tak peduli pada apa rencana dan kerja-kerja ril mereka. Anak-anak
itu tidak tahu bahwa di negara yang katanya menjunjung tinggi nilai dan etika
ini, terdapat banyak orang yang ingin menegakkan nilainya sendiri, tanpa
memberikan kewenangan kepada negara.
Jika saja anak-anak itu membaca media,
mereka akan menyaksikan gelombang aksi yang mengutuk aksi lempar bom itu.
Bangsa ini memang hanya bisa mengutuk. Seolah-olah ketika mengutuk, selesailah
semua persoalan. Padahal, mengutuk hanyalah satu reaksi sesaat, yang lalu
dilanjutkan dengan kerja-kerja cerdas untuk menata ulang formasi sosial
masyarakat yag terpecah-belah oleh doktrin dan keyakinan. Sayang, kita tak siap
dengan kerja-kerja hebat itu.
Betapa sulitnya menanamkan kesadaran
spiritual bahwa manusia itu sama, tanpa harus memandang perbedaan. Betapa
sulitnya merawat bumi dan manusia lain sebagai bagian dari diri kita. Agama
masih dilihat sebatas kosmetik politik dan kebanggaan semu. Di arena politik,
orang-orang tiba-tiba saja menjadi religius saat hendak bersaing menjadi
pejabat publik. Banyak orang yang dibohongi (pakai) ayat-ayat. Banyak
orang yang mau saja dibohongi (pakai) label keyakinan.
Kita bangga menyebut diri sebagai negeri
religius, tapi kita tak pernah bertanya, apakah ajaran agama yang indah itu
sanggup kita jelmakan dalam tatanan hukum. Kita alpa memandang, apakah keadilan
bisa menjadi payung buat semua anak bangsa, apapaun keyakinannya. Kita
mempunyai kementerian agama, namun kementerian ini tidak pernah melakukan
transformasi sosial, menanam benih kesadaran bahwa agama hadir hanya sebagai
jalan untuk menemukan diri-Nya yang penuh kuasa dan mengatur bumi dengan
hukum-hukum-Nya.
***
SAYA masih terkenang kanak-kanak itu. Saya
berharap peristiwa ini justru bukan menjadi akhir, melainkan awal bagi
kehidupan mereka. Saya berharap mereka serupa burung phoenix yang selalu
terlahir setiap kali ada maut menikam diri. Mudah-mudahan saja, peristiwa bom
ini adalah awal bagi mereka untuk memahami berbagai dinamika dan karakter
manusia.
Kalaupun mereka harus trauma, tak mengapa.
Semoga saja trauma itu tak terus-terus menghantui mereka. Bangsa ini
membutuhkan pribadi tangguh yang menjadikan masa silam sebagai titik tumpu
untuk melesat. Negeri ini membutuhkan banyak anak muda yang berpikiran jernih,
selalu memandang ke depan demi tanah air yang semakin kuat dan tidak menjadi
sarang dari generasi frustasi yang suka melempar bom.
Di masa depan, saya akan amat bahagia
mendengar kisah tentang para kanak-kanak yang terlahir kembali seusai tragedi
bom, lalu tumbuh menjadi figur hebat yang berbuat banyak untuk sekitarnya.
Semoga saja semua trauma itu bisa ditransformasi menjadi kekuatan dahsyat yang
sukar dipahami. Semoga saja mereka bisa belajar pada Muhammad putra Abdullah
yang tetap menunjukkan kasih sayangnya di tengah berbagai ketidakadilan yang
diterimanya, atau pada Isa yang rela disalib demi umat manusia. Di abad
kekinian, Mandela dan Gandhi yang menjalani masa remaja penuh nestapa dan
trauma, akan tetapi saat dewasa mereka menjadi figur hebat yang tak mau
mengutuk kegelapan lalu berbuat nekat, melainkan menyalakan sebatang lilin demi
mengatasi gelap.
Ah, saya sungguh berharap pada anak-anak
itu di masa depan.
Bogor, 13 November 2016
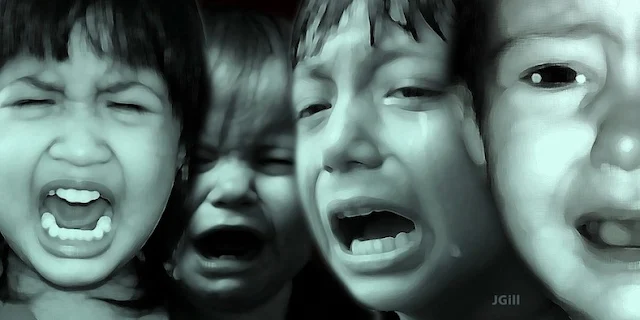
0 komentar:
Posting Komentar