Mengeja Timur dari Buritan PERAHU
 |
| tiga buku yang dibuat tim Ekspedisi Maritim Timur Nusantara |
SETIAP anak yang menemukan mainan paling
diingininya, selalu akan bersorak kegirangan. Setiap pembaca buku yang
disodorkan buku yang selalu ingin dibacanya pasti akan berreaksi serupa. Mainan
dan buku adalah jendela untuk memasuki dunia imajinasi. Mainan dan buku adalah
dua kepak sayap yang membawa pikiran beterbangan.
Di hadapan saya ada dummy atau draft tiga buku yang sungguh menarik. Ketiganya berada
dalam satu bundel bertuliskan Ekspedisi Maritim Timur Nusantara, yang ditulis
anggota tim ekspedisi. Buku pertama berjudul Pesan dari Buritan berisikan catatan perjalanan mengarungi samudera
untuk menelusuri jejak perahu kecil para pelaut tradisional Buton yang berlayar
ke timur Nusantara, di tanah-tanah eksotik Taliabu lalu ke tanah Maluku Utara
dan Maluku Kepulauan. Dua buku lainnya adalah Menatap Halaman Timur dan Hore
adalah kumpulan foto-foto menarik tentang pelayaran itu, serta sketsa para
pelaut.
Pelayaran itu dimulai dari Wakatobi, yang
sejak lama telah berkarib dengan semesta maritim, Di tanah itu, kita masih bisa
menyaksikan perahu-perahu ramping yang gesit membelah lautan, kapal-kapal kayu
berukuran besar yang masih hilir-mudik di lautan, juga bisa bertemu para nakhoda
hebat yang bahkan di tengah gelombang raksasa pun masih bisa tersenyum sembari
menghisap rokok kretek.
Saya menyukai buku ini karena beberapa
sebab. Pertama, buku ini lahir melalui proses yang tidak mudah. Penulisnya
mesti mengarungi samudera, melakukan perjalanan, lalu mencatat semua yang
disaksikannya di perjalanan itu. Penulisnya menelusuri rute kuno pelayaran
orang Buton yang terhenti akibat modernisasi sektor pelayaran. Pelayaran itu
ditempuh dengan perahu kecil yang disebut bangka.
Kedua, data-data yang disajikan penulisnya
menjadi bernilai karena data itu adalah data first hand reality. Penulisnya tidak sedang mengutip berbagai
literatur, melainkan langsung memasuki jantung realitas, mencatat segala hal
penting, lalu membagikannya kepada orang banyak.
Kerja itu menjadi begitu bernilai sebab penulisnya
sekaligus melakukan ekspedisi, pengamatan terlibat, merasakan langsung
bagaimana degup jantung para pelaut saat menyaksikan samudera, mengalami urat
nadi lautan yang kadang kala penuh gelora, dan kadang kala tenang saat
lembayung senja berarak di kejauhan.
Ketiga, ekspedisi ini menyajikan begitu
banyak mutiara-mutiara berharga berupa pengalaman, kesaksian serta perjumpaan
budaya. Membaca buku ini saya bisa merasakan bahwa para pelaut Buton datang
berperahu ke kawasan timur tidak sekadar berdagang kopra, tapi juga bertukar
budaya, menyebar silaturahmi, serta meninggalkan banyak jejak persahabatan.
Banyak di antara pelaut itu yang menepi ke darat, lalu menikah dengan warga
setempat. Mereka menjadi jangkar dari pertukaran budaya, serta menyisakan jejak-jejak
pada jalur pelayaran tradisional itu. Banyak tradisi yang masih bisa dikenali
akar kebudayaannya. Buku ini menjadi pintu masuk untuk mengeja kawasan pesisir di timur Indonesia.
 |
| rute ekspedisi |
Keempat, cara penulisnya menggambarkan
keadaan mengingatkan saya pada metode etnografi yang sering ditempuh para
antropolog. Cara penulisan di buku ini menempatkan para penulis dan peneliti sebagai
pembelajar yang datang ke lapangan untuk menyerap kearifan. Mereka membuang
jauh-jauh segala bias dan keangkuhan orang kota dan orang luar, demi satu
ikhtiar belajar dari masyarakat yang ditemuinya di perjalanan.
Pada bagian awal, penulisnya menggambarkan
ekspedisi itu dibumbui oleh jejak sejarah yakni kelapa, pelayaran rakyat, dan
perdagangan antar pulau. Kesemuanya adalah samudera di pelupuk mata
perekonomian rakyat di timur Nusantara. Berkat pelayaran dan perdagangan kelapa
itu, masyarakat di timur saling bertaut, lalu membentuk sabuk yang mengikat
banyak budaya. Laut adalah ruang luas bagi mereka untuk bertegur sapa.
Membaca perjalanan lintas pulau yang
bergerak mengikuti jalur perdagangan kopra itu mengingatkan saya pada kerja-kerja
Celia Lowe, seorang antropolog asal University of Washington. Dia menulis tentang
bagaimana ikan bius diperdagangkan dari Pulau Togean hingga pasar global di
Hongkong.
Dalam buku Wild Profusion, Celia menelusuri perjalanan ikan itu serta konflik
yang menyertainya. Dimulai dari konflik lokal, ketika suku Bajo menjadi
tertuduh di Togean demi melindungi permainan bisnis para cukong yang hendak
menyelundupkan ikan hidup itu ke Hongkong. Ternyata perdagangan itu hanya untuk
memenuhi mitos keberuntungan orang kaya di pasar global yang percaya mitos
bahwa memelihara ikan tertentu bisa membuatnya selalu beruntung.
Buku lain yang senapas dengan itu adalah Ekspedisi Cengkeh yang disusun oleh tim
Inninnawa dan Insist. Buku itu menyajikan perjalanan menyusuri cengkeh sebagai
komoditas utama yang membuat Nusantara menjadi mutiara yang diperebutkan bangsa
Eropa. Keemasan cengkeh tidak seemas nasib para petaninya, yang justru tetap
bersahaja. Nasib petani tidak seindah hebatnya kisah perdagangan cengkeh
disebabkan permainan sejumlah pengusaha dan elite.
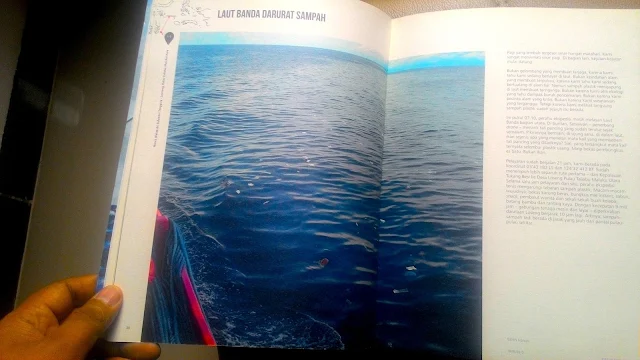 |
| beberapa tampilan halaman dalam |
Pada semua buku-buku itu, saya menemukan
apa yang disebut George Marcus sebagai multi-sited
ethnography, yakni cara untuk menemukan proses global dan memahami
interkoneksitas orang-orang dalam proses globalisasi. Metode riset ini bisa membantu
kita untuk memahami bagaimana dunia di era yang terus bergerak ini. Orang-orang,
ide-ide, dan komoditas tidak lagi terikat pada satu ruang geografis, melainkan
terus bergerak. Hanya dengan mengikuti ide, orang, atau komoditas, kita bisa
menemukan satu benang merah pengetahuan yang mendalam.
Di era internet ini, ide-ide dipertukarkan
dengan cepat dan melampaui batas-batas geografis. Orang-orang juga dengan
mudahnya berpindah-pindah, lalu menyisakan jejak di mana-mana. Bahkan komoditas
pun dengan mudahnya berpindah antar pulau dan kawasan hanya karena sentuhan
jemari yang lalu tersebar ke mana-mana berkat kabel fiber optik. Teknologi
tumbuh dengan cepat. Manusia saling terhubung dengan cepat, sesuatu yang
sebenarnya telah terjadi di masa silam. Bedanya, kabel fiber optik itu
berbentuk perahu, samudera, serta kecakapan seorang nakhoda mengarungi lautan.
Pertemuan kebudayaan itu telah terjadi melalui persahabatan di lautan, dialog
yang memperkaya pengetahuan, hingga berbagi kebaikan dengan banyak orang di
banyak pulau.
Saya menyukai filosofi para pelaut
Wakatobi sebelum berlayar, Mereka mengucap syair serupa mantra yang berbunyi bara moturu da’o. Secara harfiah
bermakna janganlah kalian moturu
(tidur) dan da’o (buruk). Pesan itu bisa ditafsir secara luas. Saat berlayar,
berhati-hatilah, kenali cuaca, pelajari arus, pahami karang, pastikan haluan,
hadapi bajak laut Terakhir, bawa diri baik-baik di rantau, pulang selamat dan
berhasil.
Para pelaut itu mengajarkan satu filosofi:
kehidupan itu serupa menjaga keseimbangan perahu dari berbagai gelombang. Di
lautan ada banyak gelombang dan ombak yang menjadi karib para pelaut. Mereka
yang memahami semua unsur semesta di sekitarnya adalah mereka yang bisa menjaga
kemudi demi mengarahkan perahu agar menggapai tujuan.
Kendari, 26 Maret 2017
BACA JUGA:


